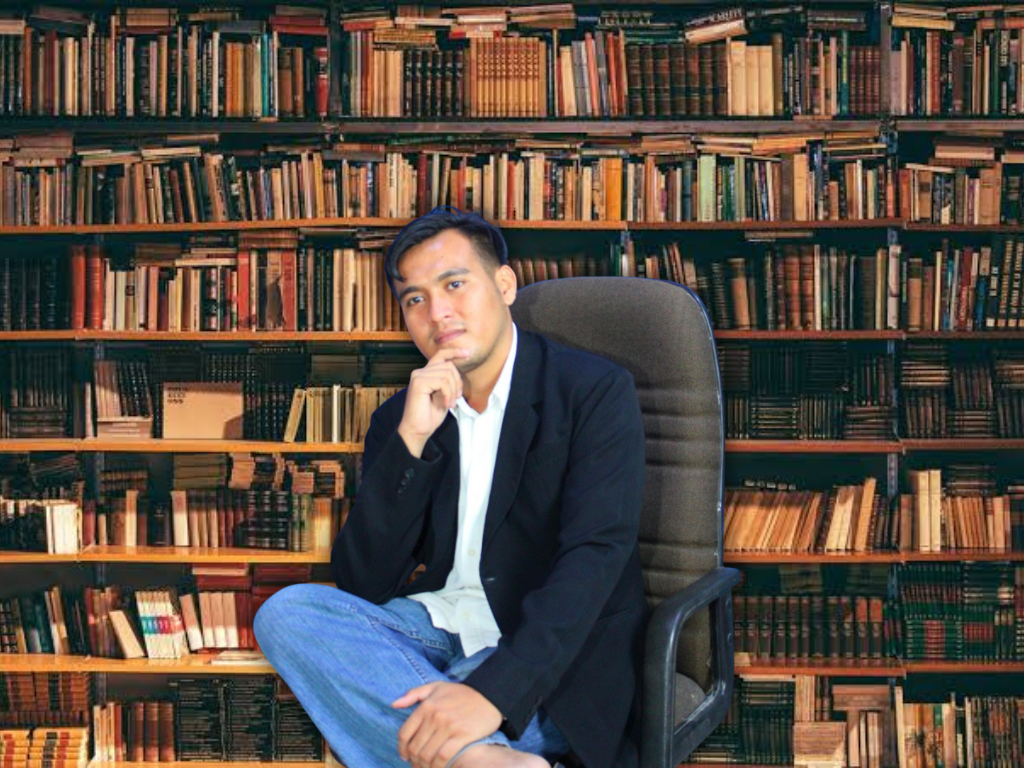Oleh: Nashrul Mu’minin, Content Writer Yogyakarta
Sebagai kader Muhammadiyah yang tumbuh dalam tradisi literasi dan keilmuan, aku tak bisa diam melihat realitas pendidikan kita hari ini. Setiap hari Ahad, aku meluangkan waktu untuk menulis dalam program Ahad Produktif sebagai wujud tanggung jawab intelektual. Di hari-hari lainnya, aku tetap menulis—tentang isu sosial, refleksi diri, hingga evaluasi kebijakan. Dari kebiasaan itu, muncul satu pertanyaan yang menghantuiku: mengapa pendidikan kita tampak gagal membentuk manusia yang kritis, solutif, dan berdaya? Apakah kurikulumnya yang salah? Atau justru kita yang belum menjalankannya dengan benar?
Kecintaanku pada aktivitas literasi membuka banyak tabir. Aku menyaksikan betapa banyak pelajar hari ini yang sekadar mengejar nilai, bukan ilmu. Mereka tahu cara menjawab soal pilihan ganda, tetapi gagap saat diminta mengungkapkan gagasan. Tak sedikit pula mahasiswa yang lulus dengan nilai tinggi, tapi bingung ketika ditanya, “Apa kontribusimu untuk masyarakat?” Semua ini membuatku berpikir bahwa mungkin bukan kurikulumnya saja yang bermasalah, melainkan ada kesalahan sistemik dalam cara kita mendekati pendidikan itu sendiri.
Pendidikan yang seharusnya menjadi ladang pembentukan karakter dan kecerdasan kolektif kini lebih mirip mesin produksi ijazah. Kurikulum terus berubah, silabus direvisi, teknologi diperbarui—namun hasilnya tetap: banyak lulusan yang kehilangan makna menjadi manusia merdeka. Pendidikan kita terlihat sibuk mengejar pencitraan capaian numerik, tetapi abai terhadap ruh pembelajaran. Para guru terbebani administratif, siswa ditumpuk tugas, sementara ruang untuk berpikir merdeka semakin sempit.
Padahal, kurikulum bukanlah satu-satunya biang keladi. Kita semua turut bertanggung jawab. Orang tua, guru, murid, dan masyarakat tak bisa terus-menerus menunjuk satu pihak. Kita kehilangan ekosistem pembelajaran yang hidup. Budaya membaca digantikan budaya menggulir layar, diskusi diganti debat kusir di media sosial. Kita membiarkan pendidikan menjadi formalitas, bukan proses aktualisasi potensi manusia seutuhnya. Inilah titik krisis yang menganga: pendidikan kehilangan ruhnya karena manusianya melupakan tujuannya.
Maka solusi pertama bukan sekadar revisi kurikulum, tetapi revisi kesadaran. Kita perlu mengembalikan hakikat pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa—bukan hanya mencetak pekerja. Kurikulum harus menjadi alat, bukan tujuan. Ia harus hidup dalam praktik, bukan sekadar dokumen. Guru harus diberdayakan, bukan dijadikan juru ketik administrasi. Siswa perlu dilatih bertanya, bukan hanya menjawab. Dan kita semua, sebagai bagian dari masyarakat, harus membangun ekosistem yang merayakan proses belajar, bukan hanya hasil akhirnya.
Aku yakin, dengan kesadaran baru ini, kita bisa memulai perubahan dari yang terkecil—dari diri sendiri. Sebagai kader Muhammadiyah, aku menjadikan menulis sebagai jalan dakwah dan pencerdasan. Di forum Ahad Produktif, kami berdiskusi tentang realitas, menajamkan nalar, dan menyampaikan ide lewat tulisan. Kami percaya, literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tapi sarana untuk membebaskan. Setiap paragraf yang kami hasilkan adalah bagian dari jihad intelektual yang diwariskan oleh KH. Ahmad Dahlan.
Implementasi semangat ini harus menyentuh akar. Di sekolah dan kampus, perlu ada ruang yang memberi kebebasan intelektual. Forum-forum seperti diskusi pelajar, lomba esai, kelas filsafat, dan kajian isu terkini harus diperbanyak. Kurikulum seharusnya membuka peluang eksplorasi gagasan, bukan mengekang dengan soal pilihan ganda. Di rumah, orang tua perlu menjadi teladan yang membaca, berdialog, dan menghargai proses belajar. Pemerintah dan sekolah hanya bisa sejauh mendesain sistem, tapi budaya belajar hanya tumbuh jika setiap individu merasa memiliki tanggung jawab.
Kesenjangan yang paling mencolok hari ini bukan hanya pada kualitas pendidikan antardaerah, tapi antara makna dan praktik pendidikan itu sendiri. Kita punya tujuan luhur dalam UU Sisdiknas, namun pelaksanaannya lebih sering melenceng. Sekolah-sekolah unggul pun belum tentu menghasilkan manusia unggul. Kesenjangan antara idealisme dan kenyataan itulah yang membuat generasi muda frustrasi. Mereka dibesarkan dalam sistem yang tak memberi ruang untuk salah, tapi juga tak memberi pelatihan untuk bijak.
Hal yang lebih menyedihkan adalah ketika pendidikan hanya dilihat sebagai jalan mendapatkan pekerjaan, bukan pengabdian. Kita menilai keberhasilan dari gaji, bukan dari kontribusi. Padahal, di ranah Muhammadiyah, pendidikan adalah jalan pembebasan, pemerdekaan, dan pemberdayaan. Kader-kader seharusnya jadi penggerak, bukan pengekor. Tetapi untuk bisa menggerakkan, kita harus belajar—bukan hanya dari buku, tapi dari kehidupan yang dituliskan dan dipikirkan secara kritis setiap hari.
Akhirnya, aku menulis esai ini sebagai bentuk refleksi dan seruan. Mari berhenti menyalahkan kurikulum semata. Tanyakan pada diri kita: sudahkah kita mendidik dengan jiwa, bukan hanya dengan sistem? Sudahkah kita menulis dan berpikir untuk membebaskan, bukan sekadar menggugurkan tugas? Jangan biarkan pendidikan hanya jadi slogan dalam dokumen negara, sementara generasinya kehilangan arah.
Sebagai kader Muhammadiyah yang menjadikan hari-hariku produktif lewat tulisan, aku percaya perubahan itu nyata—asal kita konsisten. Jangan biarkan sistem membunuh semangat belajar kita. Jadikan pena dan pikiran sebagai senjata untuk membangun masa depan. Karena pada akhirnya, tulisan tak pernah gagal membentuk manusia—yang gagal adalah ketika kita berhenti berjuang untuk mencerdaskan diri dan sesama.