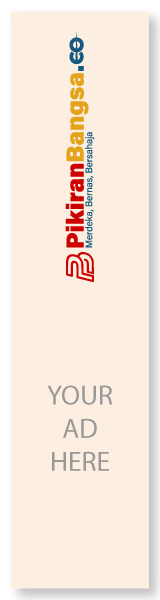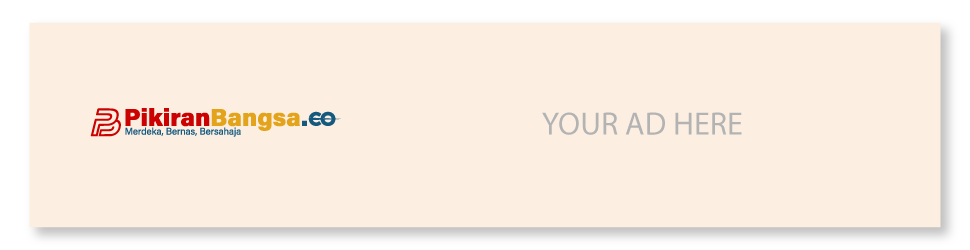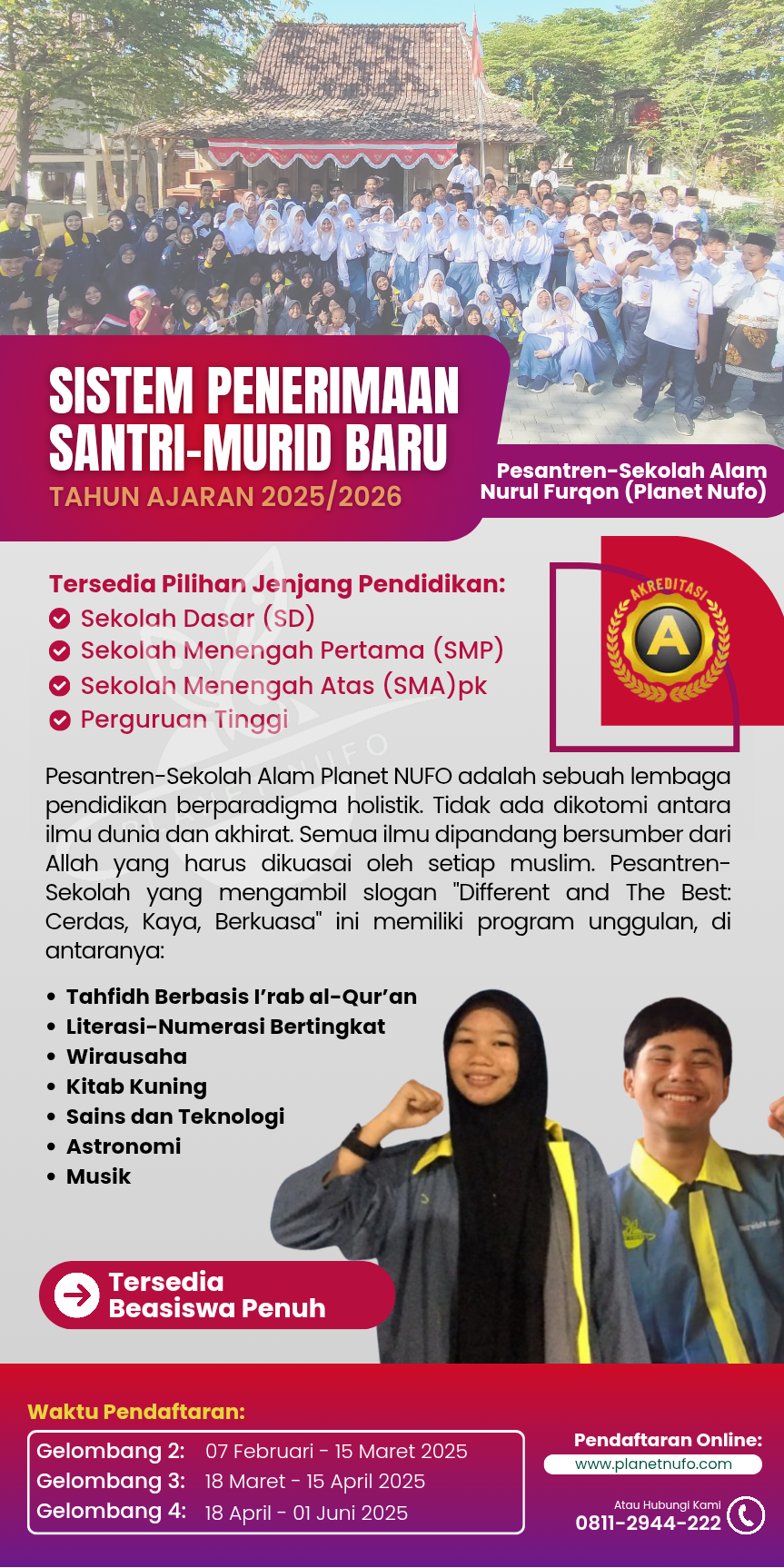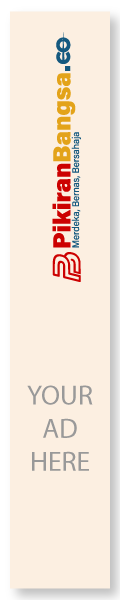Oleh: Feri Febriyanto, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Salatiga
Raja Ampat bukan sekadar gugusan pulau indah di ujung timur Indonesia. Ia adalah simbol kekayaan hayati laut tropis dunia—rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan, 550 spesies karang, serta situs budaya purba yang masih dijaga masyarakat adat. Namun di balik kemegahan ekologis itu, ancaman perlahan mengintai: ekspansi pertambangan nikel yang mulai menggerus ketenangan ekosistem demi kepentingan industri global.
Pemerintah Indonesia kini tengah gencar mendorong hilirisasi nikel sebagai bagian dari strategi transisi energi dan ekonomi hijau. Sayangnya, semangat besar ini belum sepenuhnya disertai tata kelola sumber daya alam yang bijak dan berkeadilan. Di Pulau Gag, salah satu wilayah di Raja Ampat, aktivitas tambang kembali menggeliat. Masyarakat dan pemerhati lingkungan khawatir terhadap potensi kerusakan ekosistem laut, sedimentasi, hingga hilangnya sumber penghidupan warga lokal yang selama ini bergantung pada laut dan ekowisata.
Dalam perspektif ekonomi berkelanjutan, pembangunan seharusnya tidak mengorbankan masa depan generasi berikutnya demi keuntungan sesaat. Laut Raja Ampat sejatinya menyimpan nilai ekonomi jangka panjang jika dikelola dengan prinsip konservasi dan partisipasi masyarakat. Namun ketika logika pembangunan hanya diukur dari seberapa banyak mineral yang bisa diekspor, arah pembangunan pun bergeser dari keberlanjutan menuju eksploitasi.
Persoalan ini bukan semata urusan ekonomi atau lingkungan, tetapi juga menjadi ujian nyata bagi tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Pemerintahan yang ideal harus menjunjung transparansi dalam proses perizinan, menjamin partisipasi publik, dan bersikap akuntabel terhadap dampak ekologis dari kebijakannya. Sayangnya, dalam kasus Raja Ampat, masyarakat adat sering kali tidak dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tanah dan laut mereka sendiri.
Ironi terbesar dari situasi ini adalah ketika kita di satu sisi menjual citra Indonesia sebagai “paru-paru dunia” dan negeri kepulauan yang kaya, namun di sisi lain membiarkan kerusakan sistematis terjadi di tempat-tempat paling suci secara ekologis. Ini bukan lagi soal konservasi semata, melainkan soal moralitas dalam mengelola kekuasaan dan tanggung jawab antargenerasi.
Sebagai mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, saya percaya bahwa suara publik memiliki kekuatan besar untuk mengubah arah kebijakan. Media harus menjadi ruang dialektika—bukan sekadar corong kebijakan negara, tetapi juga pelindung bagi kebenaran ekologis. Narasi yang dibangun harus menempatkan laut dan masyarakat pesisir sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek eksploitasi. Kita perlu membangun kesadaran bahwa ekonomi hijau yang sejati tidak akan lahir dari luka-luka ekologis yang dibiarkan terbuka.
Raja Ampat harus diselamatkan, bukan karena keindahannya di mata wisatawan asing, tetapi karena ia adalah warisan bangsa, bahkan warisan dunia. Warisan yang tak dapat digantikan oleh kilauan nikel atau logam tanah jarang.
Pertanyaan “siapa yang melindungi warisan laut Nusantara” sesungguhnya kembali kepada kita semua—pada keberanian untuk bersuara, berjuang, dan bertindak demi masa depan yang lestari.
Saya yakin, perubahan bisa dimulai dari sini—dari tulisan ini. Karena saya anak KPI. Dan bagi mereka yang bersungguh-sungguh, tak ada jalan yang benar-benar buntu. Jika ada kemauan, di situ pasti ada jalan.