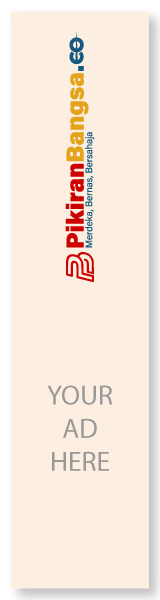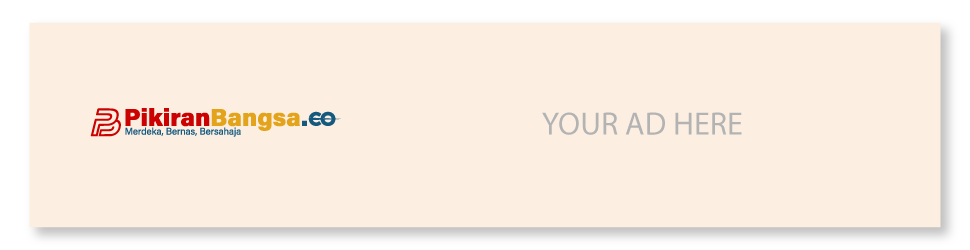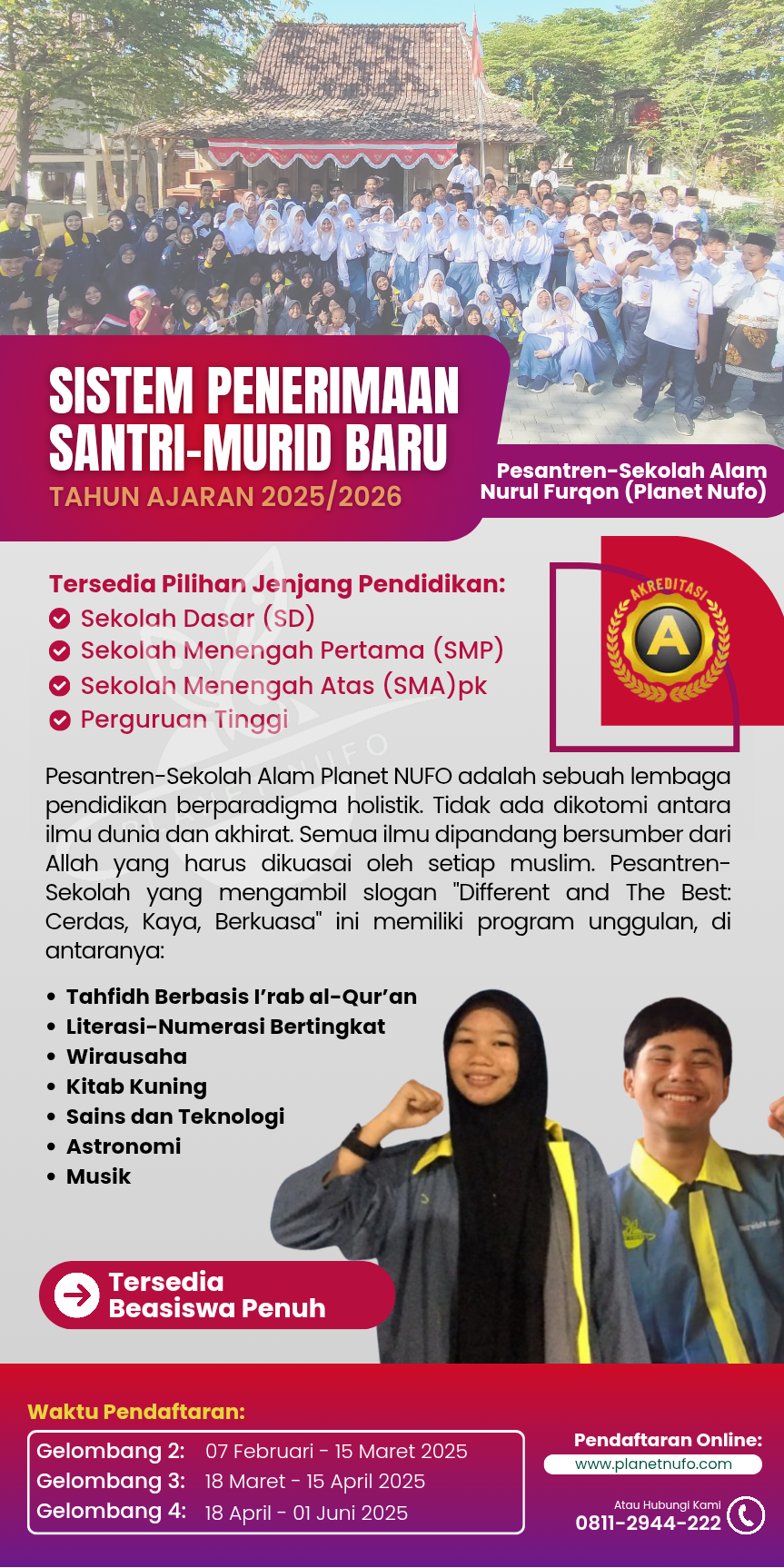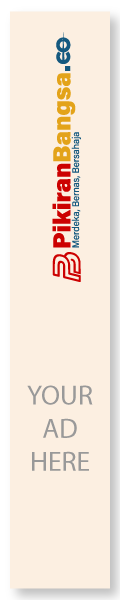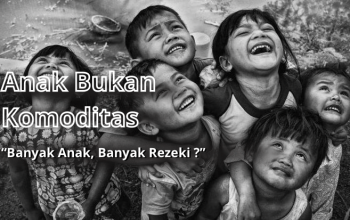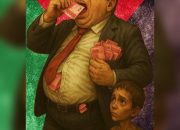Oleh: Bela Novi Rahmawati, Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Kita menyaksikan perubahan besar dalam cara kita berinteraksi sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial. Media sosial seharusnya menjadi tempat yang positif di mana orang berbagi ide, informasi, dan menghargai satu sama lain. Ironisnya, budaya komentar kasar semakin berkembang di tempat ini. Hal ini pasti mencerminkan erosi etika yang semakin umum dalam komunikasi, tertutama di kalangan pengguna media sosial Indonesia. Komentar kasar, ujaran kebencian, dan penghinaan selalu ada di dunia maya.
Philip Zimbardo mengembangkan teori Deindividuasi, yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Menurut Zimbardo, Ketika orang anonim, seperti di internet, mereka cenderung melakukan tindakan yang lebih ekstrim dan tidak terkendali. Orang-orang yang merasa identitas mereka dilindungi di media sosial memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat mereka secara kasar dan tidak bertanggung jawab. Anonimitas yang ditawarkan oleh platform media sosial seakan menghapus batasan sosial dan moral dalam interaksi tatap muka. Hal ini meningkatkan kecenderungan individu untuk menggunakan Bahasa kasar tanpa mempertimbangkan efeknya pada orang lain. (Rulli Nasrullah, 2018).
Fenomena keterasingan sosial atau anomie yang dijelaskan oleh Emile Durkheim dalam teori Struktural-Fungsionalisme juga sejalan dengan budaya komentar kasar ini. Durkheim berpendapat bahwa norma-norma sosial sangat penting untuk menjaga masyarakat tata tertib dan harmonis. Namun, standar ini seringkali tidak jelas atau bahkan tidak diterapkan dengan tegas di media sosial. Hal ini menyebabkan kekosongan moral di mana pengguna merasa tidak ada aturan yang mengikat mereka untuk berperilaku sopan dan berbudi pekerti. Tidak adanya norma sosial yang mengatur perilaku menyebabkan komentar kasar dan perilaku negatif pun meningkat. (Emile Durkheim, 2006).
Dalam konteks Indonesia, situasi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Banyak pengguna media sosial yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara berkomunikasi dengan baik dan beretika di internet. Sebagian besar dari mereka masih terjebak dalam sikap emosional dan tidak bijak dalam merespons perbedaan pendapat. Namun, keterampilan digital yang baik dapat membantu pengguna menggunakan media sosial dengan lebih bertanggung jawab dan etika berkomunikasi yang sesui dengan norma sosial.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2021, literasi digital masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, meskipun populasi internet semakin meningkat. Ini berkontribusi pada banyaknya komentar kasar dan ujaran kebencian di media sosial. (Kominfo, 2021).
Tidak hanya itu, fenomena ini diperburuk oleh algoritma yang digunakan oleh platform media sosial. Algoritma yang dimaksudkan untuk menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan dan preferensi pengguna cenderung memperkuat perspektif ekstrim, menciptakan echo chamber—ruang di mana orang hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sepemikiran dengan mereka—dan menciptakan ruang di mana orang hanya berinteraksi dengan orang-orang yang setuju dengan mereka. Ini semakin menjauhkan orang dari perspektif yang berbeda dan meningkatkan polarisasi sosial.
Sikap intoleran dan pembenaran terhadap komentar kasar, tertutama terhadap kelompok atau individu yang berbeda pandangan, meningkat sebagai akibat dari fenomena ini. Orang-orang biasanya dipandang sebagai “musuh” atau “pesaing”, dan kritik kasar dianggap sebagai cara yang sah untuk membela diri. (Sumber: Alamsyah, R., Dampak Polaritas Sosial Akibat Media Sosial di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2020).
Budaya komentar kasar ini memiliki efek jangka panjang pada masyarakat dan korban. Korban komentar kasar seringkali mengalami gangguan mental seperti kecemasan, stres, atau bahkan depresi. Selain itu, penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Pusat Pengendalian Penyakit (CDC) menunjukkan bahwa ujaran kebencian dan cyberbullying dapat menyebabkan masalah Kesehatan mental yang serius. Meskipun belum ada penelitian menyeluruh tentang efek psikologis komentar negatif di media sosial di Indonesia, tren saat ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mengaku tertekan karenanya. (Sumber: Pusat Pengendalian Penyakit (CDC), Cyberbullying dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Remaja, 2020).
Pendidikan etika komunikasi digital semakin penting. Perluasan literasi digital di institusi Pendidikan tinggi dapat menjadi langkah awal yang sangat baik. Jika orang tahu cara berkomunikasi secara sopan dan bertanggung jawab di media sosial, mereka diharapkan dapat lebih bijak dalam berinteraksi dan menghindari perilaku negatif. Selain itu, hal ini akan meningkatkan kesadaran untuk menghargai pendapat lain dapat menciptakan ruang digital yang lebih baik.
Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia, masyarakat harus dididik tentang sanksi hukum yang dapat diterima oleh mereka yang melakukan ujaran kebencian atau komentar kasar. Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Semua orang yang menggunakan media sosial harus menyadari bahwa apa pun yang mereka katakan atau lakukan dapat mempengaruhi orang lain. Karena pentingnya berkomunikasi dengan cara yang etis, kita harus berpikir dua kali sebelum membuat komentar yang kasar.
Dalam masyarakat Indonesia, nilai gotong royong dan musyawarah adalah nilai yang sangat penting ntuk diterapkan di internet. Kita dapat membangun lingkungan media sosial yang lebih damai dan menghargai satu sama lain dengan mempertahankan prinsip-prinsip ini. Diharapkan bahwa pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial bekerja sama untuk mengurangi komentar negatif. Dengan meningkatkan literasi digital dan kesadaran sosial, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan penuh penghargaan, sesuai dengan Pancasila, dasar negara kita.