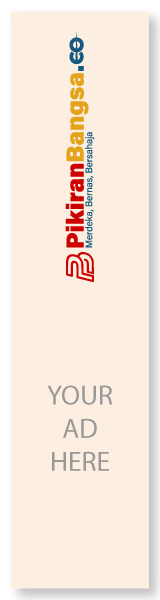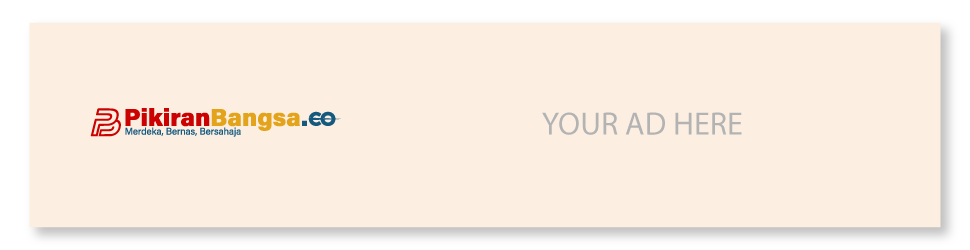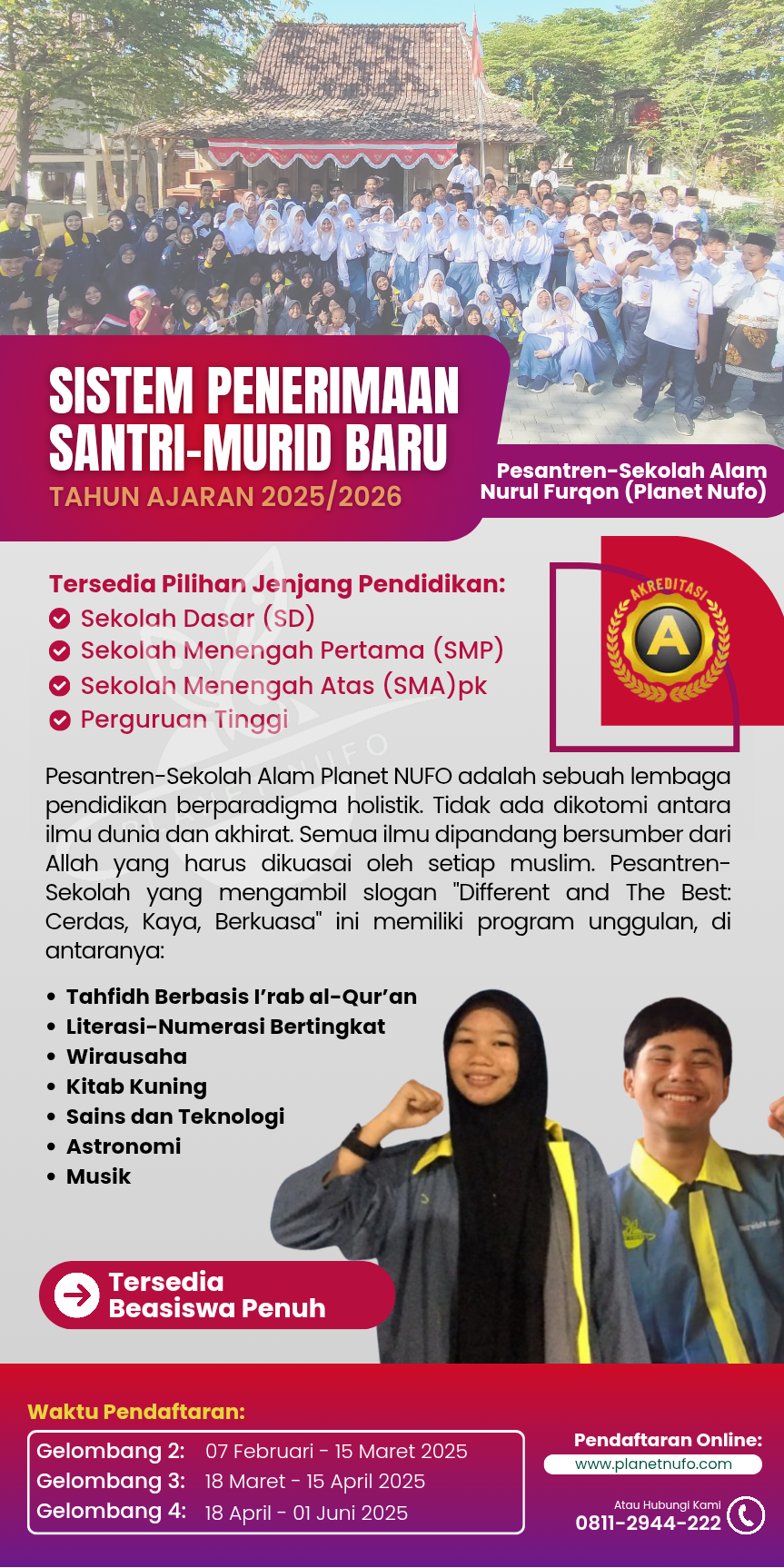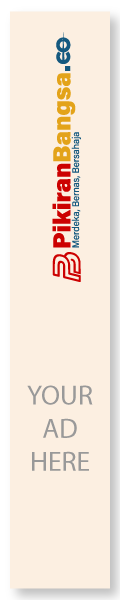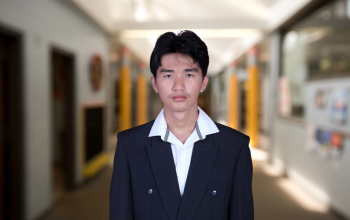Oleh: Ellysa Rossa Maharani, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta
Setiap mahasiswa pasti pernah merasakan rasa cemas yang khas menjelang tenggat waktu pengumpulan tugas. Rasanya seperti adrenalin dan panik melebur menjadi satu, membuat otak ingin tetap bekerja meski mata sudah menolak terjaga. Berada di sudut ruangan yang gelap dengan kopi yang mulai dingin dan layar laptop yang terus berkedip dari malam hingga dini hari, kita menemukan diri kita sedang melakukan hal yang sama, mengorbankan waktu tidur demi mengejar deadline.
Begadang sudah menjadi suatu kebiasaan bahkan tradisi di kalangan mahasiswa. Ada yang melakukannya karena menunda pekerjaan terlalu lama, ada pula yang mendapatkan ide baru saat tugas telah mendekati deadline. Namun, apa pun alasannya, pola yang sama akan terulang, tugas dimulai saat malam menjelang, dan baru selesai ketika pagi sebelum tugas harus dikumpulkan. Setelah selesai, tubuh yang lelah, kepala pening tapi terasa lega sekaligus bangga karena berhasil menyelesaikan sesuatu. Ironisnya, kita merayakan pencapaian itu dengan mata panda dan stress yang menumpuk di pikiran kita.
Fenomena ini sering dianggap hal biasa. “Namanya juga mahasiswa,” begitu kata banyak orang. Kalimat sederhana itu seperti membenarkan kebiasaan tidak sehat yang kita lakukan demi produktivitas palsu. Namun, ketika dianalisis lebih dalam, kebiasaan begadang bukan sekadar masalah waktu tidur yang terganggu, melainkan juga cerminan tekanan yang dialami mahasiswa dalam sistem akademik modern.
Di dunia yang serba cepat ini, standar keberhasilan sering diukur dari seberapa sibuk seseorang. Semakin sibuk, semakin dianggap berprestasi. Mahasiswa pun terseret dalam pola pikir yang sama, takut tertinggal, takut dinilai tidak cukup ambisius. Akibatnya, mereka memaksa diri untuk bekerja sampai larut malam, mengabaikan istirahat demi mengejar hasil kerja. Jam tidur pun menjadi sesuatu yang “bisa diabaikan,” seakan tidak sepenting laporan praktikum atau esai yang harus diserahkan besok pagi.
Namun, di balik semua itu, ada kelelahan yang jarang ditampilkan. Banyak mahasiswa yang merasa tidak punya pilihan selain begadang. Mereka harus menyeimbangkan tugas kuliah, pekerjaan sambilan, organisasi, ataupun kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, tidur dianggap sebagai kemewahan, bukan kebutuhan. Rasa bersalah pun muncul setiap kali mencoba beristirahat. “Kalau aku tidur sekarang, tugas ini tidak akan selesai,” begitu alasan yang terngiang di kepala. Lama-kelamaan, tubuh dan pikiran terbiasa dengan tekanan, hingga lupa cara beristirahat walaupun hanya sebentar.
Sebenarnya, tidur bukan hanya sekadar istirahat dari kegiatan.
Tidur merupakan cara tubuh dan otak untuk memulihkan diri secara alami. Beragam penelitian mengindikasikan bahwa kurang tidur dapat menurunkan kemampuan fokus, memperlambat respons otak, serta meningkatkan tingkat stres. Dengan kata lain, mengorbankan tidur untuk mengejar produktivitas sebenarnya berujung pada penurunan kualitas kerja itu sendiri. Kita memang menyelesaikan tugas, tetapi dengan hasil yang mungkin tidak maksimal.
Ada ironi yang menarik di sini, kita begadang untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik, tapi justru membuat kita tidak mampu berpikir jernih. Kita begadang untuk menyelesaikan tugas, memang benar tugas itu selesai, namun tidak dengan hasil yang maksimal. Mungkin inilah yang membuat banyak mahasiswa merasa terus lelah bahkan setelah semua tugas selesai. Tubuh mereka bekerja, dan pikiran mereka tidak pernah benar-benar beristirahat.
Kemudian, apa yang membuat kebiasaan ini begitu sulit untuk dihentikan? Sebagian jawabannya terletak pada sistem yang menuntut banyak hal dilakukan dalam waktu singkat. Tenggat waktu sering kali berdatangan bersamaan, disaat dosen menginginkan hasil terbaik, sementara mahasiswa hanya memiliki dua tangan dan satu pikiran. Di pihak lain, perkembangan teknologi membuat kita semakin sulit untuk membedakan antara waktu bekerja dan waktu beristirahat. Notifikasi, pesan grup, atau sekadar hasrat untuk “memeriksa” media sosial mengubah malam yang seharusnya damai menjadi lembur tanpa akhir.
Meski begitu, menyalahkan sistem saja tidak cukup. Kita juga perlu belajar mengenali batas diri. Ada kalanya, tubuh sudah memberi tanda untuk berhenti, tetapi kita memaksa diri karena takut terlihat malas. Padahal, istirahat bukan bentuk kemalasan, melainkan cara untuk menjaga agar diri tetap waras. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menormalisasi begadang sebagai simbol kerja keras.
Bekerja keras memang penting, tapi bekerja cerdas jauh lebih berharga.
Belajar mengelola waktu tidak hanya tentang disiplin saja, tapi juga tentang menghargai diri sendiri. Tidak semua hal harus diselesaikan dengan mengorbankan waktu tidur. Seringkali, hasil terbaik datang dari pikiran yang segar setelah beristirahat walaupun hanya sebentar. Memang tidak mudah mengubah kebiasaan yang sudah lama dianggap wajar. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil, seperti menyusun jadwal lebih awal, mencoba untuk tidak menunda pekerjaan, dan mematikan layar handphone ketika mata sudah lelah.
Pada akhirnya, hidup di dunia akademik tidak seharusnya membuat kita kehilangan keseimbangan. Tidur bukan simbol kemalasan, melainkan bagian dari produktivitas itu sendiri. Mungkin, yang perlu kita kejar bukan lagi sekadar deadline, tetapi juga belajar untuk mengenali kapan kita harus berhenti. Karena apa gunanya tugas yang sempurna jika dikerjakan dengan tubuh yang sakit. Mengorbankan waktu tidur memang bisa membuat tugas selesai, tapi tidak selalu membuat kita berhasil. Kadang, keberhasilan justru ada pada waktu otak pulih dan tubuh yang segar.