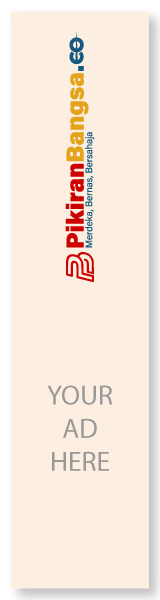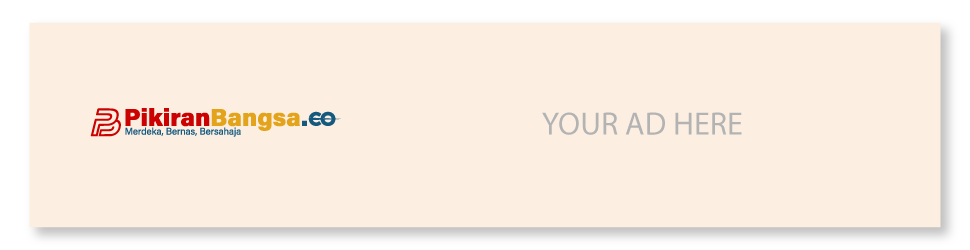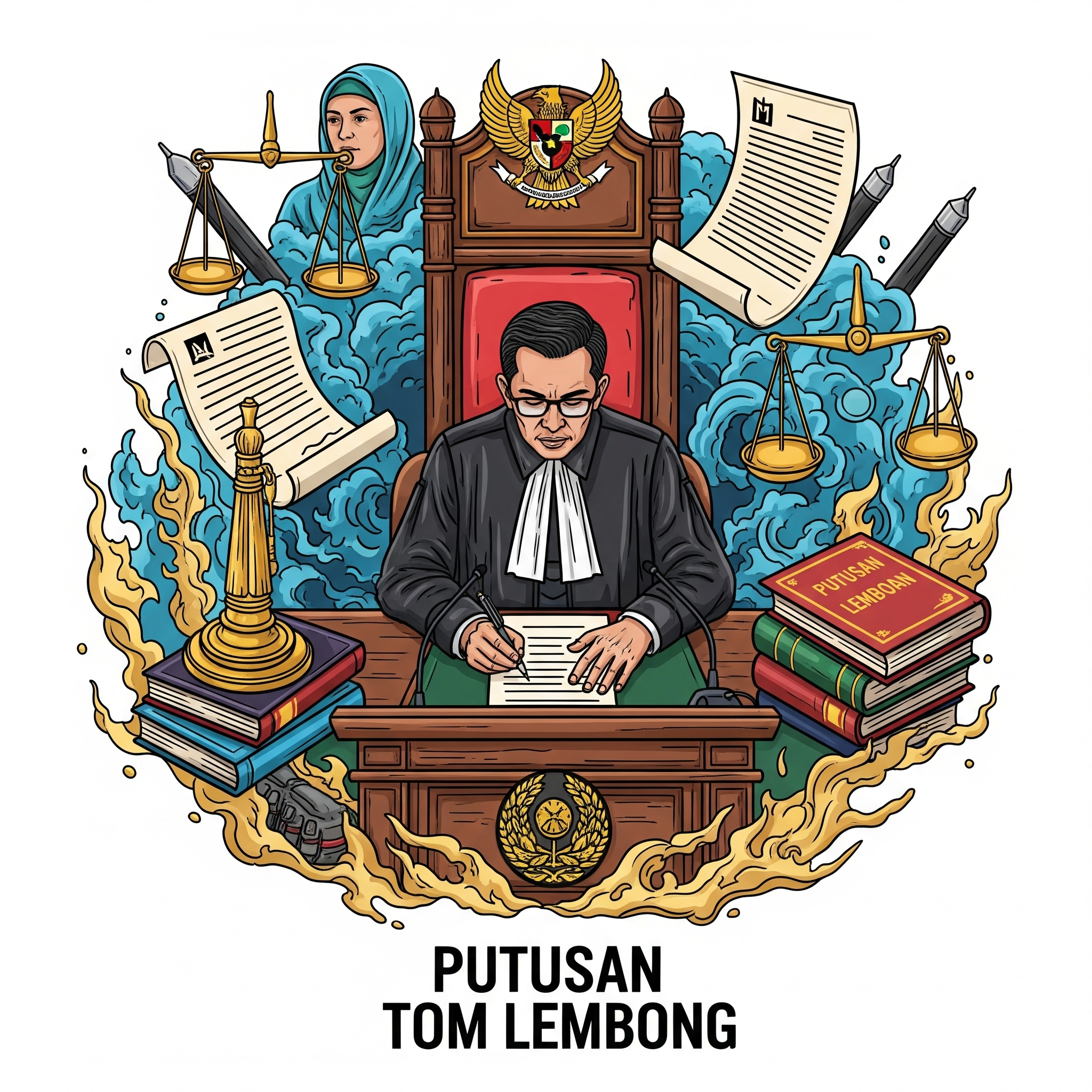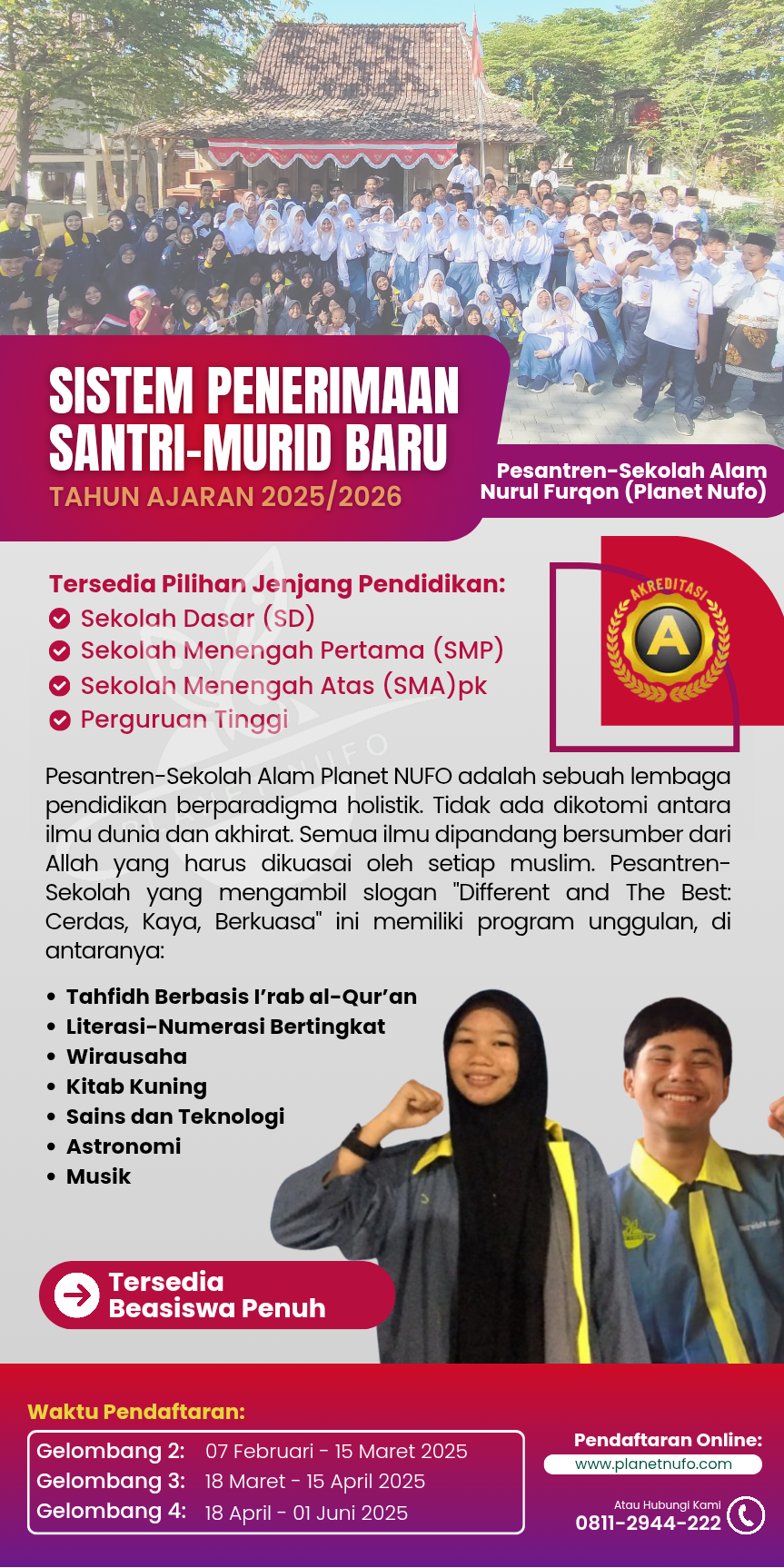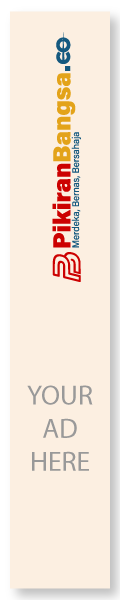Oleh: Kodrat Alamsyah, S.H., Ketua Bidang Kajian Strategis PW GPII Jawa Tengah.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Thomas Trikasih Lembong dalam kasus impor gula memunculkan pertanyaan mendasar: bisakah seseorang dipidana korupsi tanpa menerima keuntungan apa pun? Hakim menyatakan tidak ditemukan bukti aliran dana maupun keuntungan pribadi yang diperoleh Lembong, tetapi ia tetap dihukum. Kasus ini mengusik nalar hukum, etika keadilan, dan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memang memungkinkan seseorang dipidana karena perbuatannya menguntungkan orang lain atau korporasi, meskipun ia sendiri tidak memperoleh apa-apa. Sementara Pasal 3 UU Tipikor menyasar penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Namun, dalam praktiknya, banyak pakar hukum yang menilai penggunaan pasal-pasal ini seringkali overstretched, terlalu luas ditafsirkan hingga melabrak asas-asas hukum pidana modern.
Prof. Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Hukum Pidana UI, dalam berbagai forum menegaskan bahwa “tidak semua tindakan administratif yang berujung pada kerugian negara adalah korupsi.” Ia menyebut pentingnya membedakan antara maladministrasi dan delik korupsi. Sebab tidak adanya mens rea (niat jahat) dalam suatu tindakan seharusnya menggugurkan unsur pidananya.
Hal serupa juga diutarakan oleh Prof. Romli Atmasasmita, salah satu perancang UU Tipikor, yang menyatakan bahwa “tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan yang disengaja, tindakan pejabat seharusnya hanya diproses secara administratif, bukan pidana.” Ini menjelaskan bahwa pengambilan keputusan yang salah belum tentu menjadi tindak pidana, apalagi jika niat memperkaya diri atau pihak tertentu tidak terbukti.
Titik soal kasus Lembong terletak pada kebijakan impor gula yang memberikan izin kepada swasta, bukan BUMN. Padahal, realitasnya, banyak pejabat publik lain melakukan kebijakan serupa tanpa pernah diperkarakan. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan kesan kuat adanya penegakan hukum yang diskriminatif dan politisasi aparat penegak hukum. Apalagi Lembong dikenal sebagai tokoh dengan pemikiran ekonomi liberal dan sempat menjadi kritikus kebijakan pemerintah pasca tidak lagi menjabat.
Bahkan dalam sidang pleidoinya, Lembong menyatakan, ‘Saya tidak pernah menerima uang sepeser pun…’ Putusan juga menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti aliran dana maupun keuntungan pribadi. Dengan fakta tersebut, sangat wajar publik menilai bahwa yang sedang dihukum bukanlah perbuatan kriminal dalam arti hukum pidana, melainkan keputusan kebijakan yang kini dikriminalkan.
Praktik semacam ini menyuburkan apa yang oleh John Rawls dalam “Theory of Justice” disebut sebagai “arbitrariness in justice”—keadilan yang diterapkan tidak secara konsisten, melainkan tergantung siapa pelakunya dan dalam konteks kekuasaan seperti apa ia berada.
Jika logika penghukuman terus dibiarkan tanpa mensyaratkan niat jahat atau pengetahuan atas keuntungan pihak lain, maka semua pejabat publik yang mengambil keputusan strategis dengan konsekuensi fiskal dapat dipidana. Kriminalisasi terhadap diskresi adalah bahaya laten dalam sistem hukum kita. Ia menciptakan ketakutan sistemik bagi pejabat publik, sekaligus membuka celah penyalahgunaan hukum oleh mereka yang berkuasa.
Sebagai bagian dari komunitas akademik di bidang hukum, saya tidak sedang membela individu tertentu. Yang saya perjuangkan adalah prinsip keadilan yang berpijak pada nalar sehat dan integritas hukum. Sebab hukum yang ideal bukanlah hukum yang sibuk menghukum, melainkan hukum yang bekerja menjaga proporsionalitas, akuntabilitas, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Jika hukum tetap memidana orang yang tak menerima keuntungan, tak menyuruh siapa pun, tak tahu siapa yang untung, hanya karena kebijakannya ternyata berdampak fiskal, maka pertanyaannya bukan lagi “di mana letak korupsinya?”, melainkan “siapa yang akan dihukum setelah ini?”