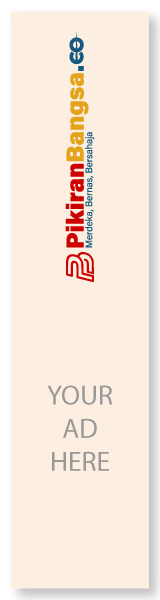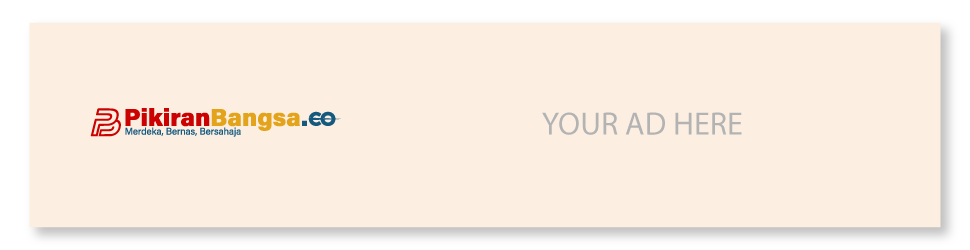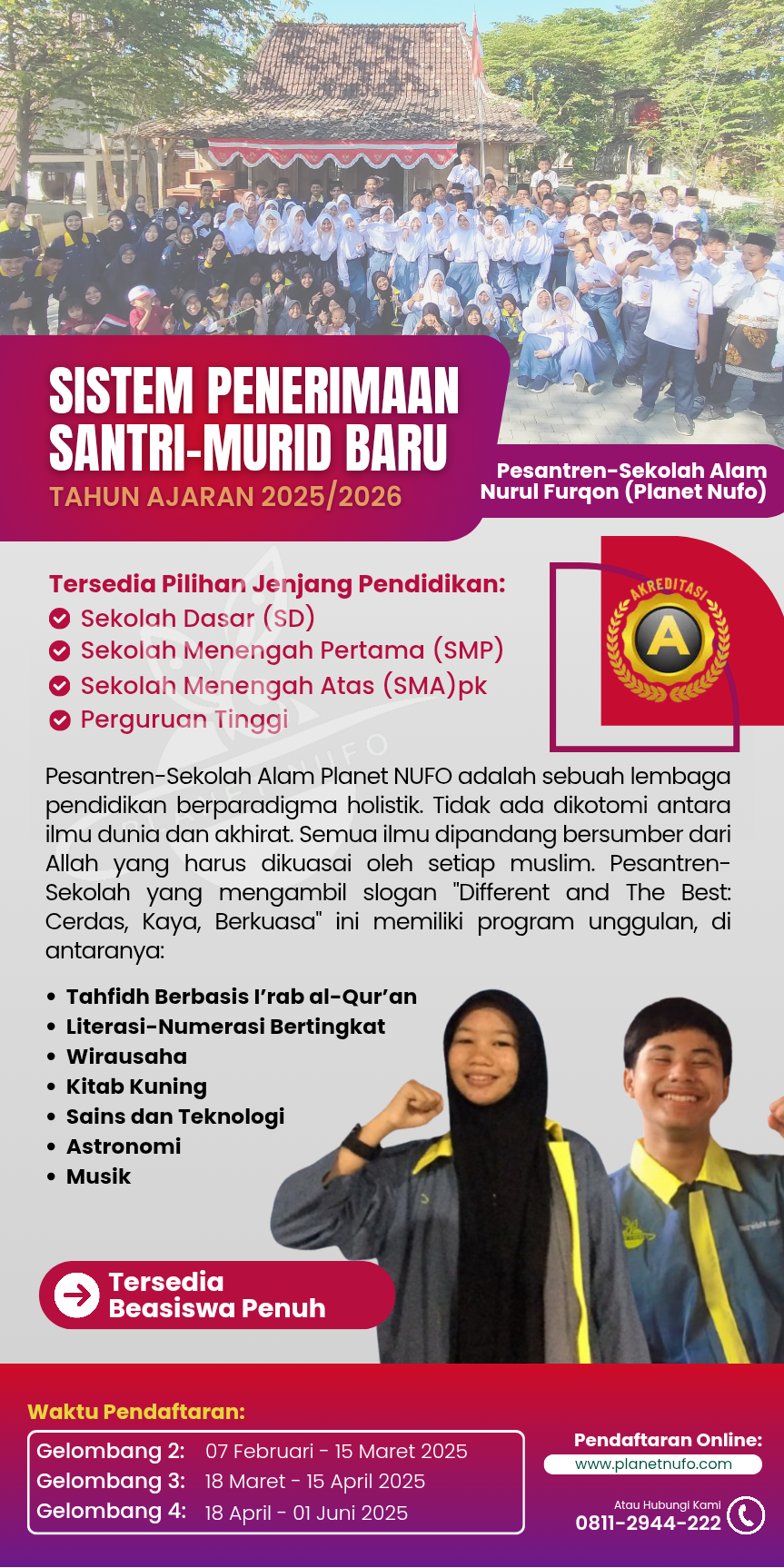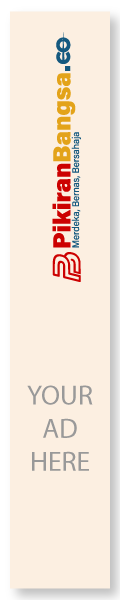Fenomena munculnya 17+8 tuntutan rakyat dalam demonstrasi nasional terbaru dapat dipahami sebagai refleksi krisis multidimensi yang tengah dihadapi Indonesia. Tuntutan tersebut tidak hanya bersifat politis dalam arti sempit, melainkan mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hak-hak fundamental warga negara. Hal ini menandakan bahwa problematika bangsa telah melampaui persoalan prosedural demokrasi dan menyentuh aspek substansial yang berkaitan dengan keadilan sosial, legitimasi kekuasaan, dan keberlanjutan kontrak sosial.
Dalam kerangka filsafat politik, gerakan rakyat ini dapat dianalisis melalui konsep volonte generale yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau. Kontrak sosial yang ideal mensyaratkan bahwa kehendak umum harus menjadi landasan legitimasi negara. Akan tetapi, praktik politik di Indonesia justru memperlihatkan pergeseran dari prinsip tersebut. Lembaga-lembaga perwakilan cenderung menjadi instrumen kepentingan oligarki, sehingga ruang representasi rakyat mengalami delegitimasi. Dengan demikian, 17+8 tuntutan rakyat dapat ditafsirkan sebagai upaya kolektif untuk merekonstruksi kontrak sosial yang telah melemah, sekaligus menegaskan kembali kedaulatan rakyat sebagai basis legitimasi negara.Kondisi ini dapat pula dijelaskan dengan perspektif Nietzsche mengenai nihilisme politik. Demokrasi yang secara prosedural berjalan, tetapi gagal menghadirkan keadilan substantif, menimbulkan kekosongan makna dan mereduksi nilai-nilai politik menjadi sekadar formalitas. Dalam situasi demikian, gerakan rakyat dapat dipahami sebagai manifestasi will to power kehendak untuk mengafirmasi nilai baru dan merebut kembali makna politik yang sejati. Politik, dalam konteks ini, harus dikembalikan kepada rakyat sebagai subjek, bukan sekadar dimonopoli oleh elite yang bertumpu pada kekuatan modal.
Secara historis, munculnya tuntutan rakyat di Indonesia bukanlah hal baru. Tritura pada 1966 dan Reformasi 1998 merupakan contoh artikulasi krisis legitimasi yang direspons oleh rakyat melalui gerakan massa. Namun, yang membedakan situasi saat ini adalah luasnya spektrum tuntutan yang diajukan. Jika pada masa lalu fokus utama adalah perubahan rezim atau sistem politik, maka 17+8 tuntutan rakyat meliputi aspek keadilan ekonomi, perlindungan sosial, hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta isu lingkungan hidup. Kompleksitas ini mengindikasikan bahwa persoalan bangsa bersifat struktural dan multidimensi, sehingga solusi yang dibutuhkan pun tidak dapat berhenti pada reformasi prosedural, melainkan harus melibatkan transformasi paradigma pembangunan dan pengelolaan kekuasaan.
Kerangka keadilan John Rawls dalam A Theory of Justice menawarkan perspektif kritis untuk membaca situasi ini. Prinsip keadilan sebagai fairness menekankan bahwa institusi sosial harus memprioritaskan kelompok yang paling lemah. Akan tetapi, realitas Indonesia menunjukkan kegagalan dalam implementasi prinsip tersebut. Ketimpangan ekonomi semakin melebar, eksploitasi sumber daya alam berjalan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan, dan kelompok rentan seperti buruh, petani, serta masyarakat adat sering kali terpinggirkan dari agenda pembangunan. Dengan demikian, tuntutan rakyat dapat dipandang sebagai upaya untuk menegaskan kembali prinsip keadilan distributif yang terabaikan.
Filsafat eksistensialisme, khususnya pemikiran Jean-Paul Sartre, juga relevan untuk memahami tindakan kolektif rakyat. Menurut Sartre, manusia memiliki kebebasan radikal yang tidak dapat ditanggalkan, meskipun sering kali teralienasi oleh struktur sosial dan politik. Demonstrasi rakyat dengan 17+8 tuntutannya adalah bentuk praksis eksistensial, yakni tindakan sadar untuk menolak keterasingan dan menegaskan eksistensi sebagai subjek politik yang otonom. Dalam kerangka ini, gerakan rakyat bukanlah sekadar protes praktis, melainkan ekspresi kebebasan yang inheren dalam diri manusia sebagai makhluk politik.
Paradoks demokrasi Indonesia semakin jelas terlihat secara prosedural demokrasi tetap berjalan, tetapi secara substantif kekuasaan terjebak dalam dominasi oligarki. Pemilu, parlemen, dan mekanisme representasi memang berlangsung, tetapi substansi kedaulatan rakyat sering tereduksi oleh kekuatan modal, patronase politik, serta praktik korupsi yang sistemik. Fenomena ini memperlihatkan kontradiksi antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Maka, 17+8 tuntutan rakyat dapat diposisikan sebagai kritik struktural terhadap paradoks tersebut sekaligus peringatan bahwa jarak antara negara dan rakyat berpotensi semakin melebar jika tidak ada koreksi fundamental.
Jalan keluar dari krisis ini menuntut hadirnya politik etis. Politik etis bukan sekadar retorika moral, melainkan praktik nyata yang menempatkan rakyat sebagai pusat. Ia menuntut keberanian untuk memutus dominasi oligarki, mengembalikan legitimasi pada partisipasi rakyat, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan dalam kerangka keberlanjutan dan keadilan sosial. Politik etis menuntut pengakuan atas rakyat sebagai subjek politik yang menentukan arah bangsa, bukan sekadar sebagai objek kebijakan pembangunan.
Dengan demikian, 17+8 tuntutan rakyat dapat dibaca sebagai cermin yang memperlihatkan luka bangsa sekaligus harapan transformasi. Ia adalah kritik terhadap kegagalan negara dalam memenuhi janji konstitusi, tetapi juga sekaligus undangan untuk membangun tatanan politik yang lebih adil dan bermakna. Jika negara memilih untuk mengabaikan tuntutan tersebut, sejarah menunjukkan bahwa krisis legitimasi dapat berkembang menjadi delegitimasi total. Namun, apabila negara merespons dengan kebijaksanaan, tuntutan ini justru dapat menjadi momentum koreksi struktural yang memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.