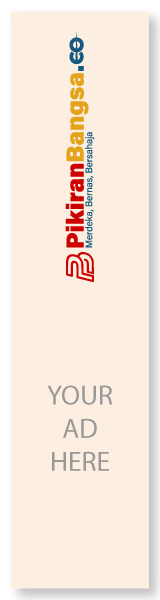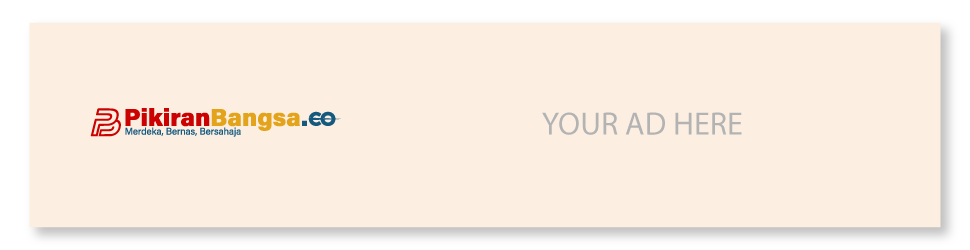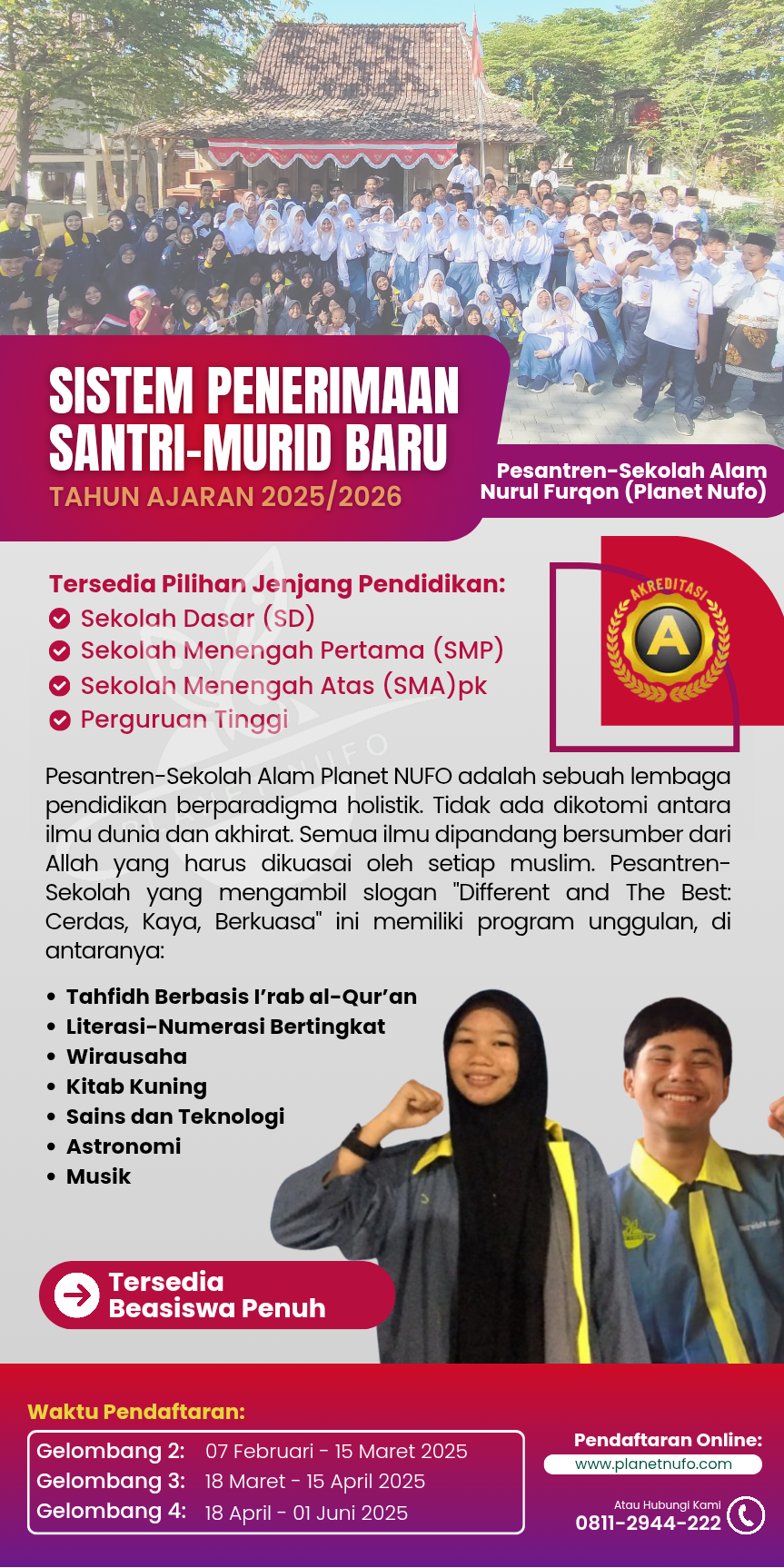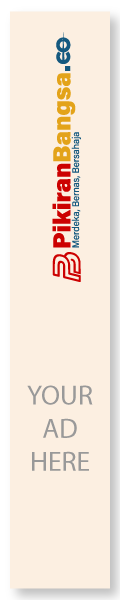Oleh: T.H. Hari Sucahyo, Peminat bidang Sosial, Politik, dan Humaniora, Penggagas Lingkar Studi Adiluhung dan Kelompok Studi Pusaka AgroPol
Wacana pengusulan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali menyentak ruang publik. Bersamaan dengan proses penilaian calon-calon pahlawan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial, nama Soeharto yang selama ini menjadi simbol rezim Orde Baru kembali mencuat di tengah nama-nama lain seperti K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), K.H. Bisri Sansuri, hingga Idrus bin Salim Al-Jufri.
Di antara mereka, Soeharto adalah yang paling kontroversial. Sebagian memandangnya sebagai “Bapak Pembangunan,” sementara sebagian lain mengingatnya sebagai figur yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia berskala besar dan praktik otoritarianisme yang membekap bangsa selama lebih dari tiga dekade.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengemukakan bahwa semangat “kerukunan dan kebersamaan” menjadi dasar pengusulan tahun ini. Bahkan ia mengutip falsafah Jawa mikul duwur mendem jero, sebuah prinsip untuk menjunjung tinggi kebaikan dan menyimpan kesalahan dalam-dalam. Ketika prinsip ini dijadikan dasar untuk mengangkat tokoh negara sebagai pahlawan nasional, perlu ada refleksi lebih dalam: apakah kita tengah mendorong rekonsiliasi, atau justru menghapus jejak sejarah dengan narasi baru yang kompromistis?
Gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan administratif atau bentuk pengakuan birokratis. Ia adalah penanda simbolik yang mengukuhkan siapa yang patut dikenang dan diteladani oleh bangsa. Dalam konteks itu, penganugerahan gelar ini menjadi arena pertarungan memori: tentang siapa yang patut dikenang, dan siapa yang patut dilupakan. Maka, ketika negara hendak memberikan gelar tersebut kepada Soeharto, muncul pertanyaan tajam: pahlawan untuk siapa?
Bagi sebagian kalangan, Soeharto dipandang sebagai tokoh yang berhasil menstabilkan kondisi politik dan ekonomi pasca-kekacauan 1965. Ia membawa Indonesia ke era pembangunan, industrialisasi, dan swasembada pangan. Ia pula yang menjaga keutuhan NKRI dari ancaman separatisme dan memodernisasi angkatan bersenjata. Namun kita tidak bisa menilai seorang pemimpin hanya dari pencapaian teknokratis, seolah sejarah adalah laporan kinerja. Apalagi jika pencapaian itu berdiri di atas luka dan penderitaan yang disisihkan dari narasi resmi.
Jejak pelanggaran HAM di masa kekuasaan Soeharto bukan sekadar catatan kelam, tapi tragedi yang belum pernah mendapat pertanggungjawaban moral maupun yudisial yang tuntas. Tragedi 1965, di mana ratusan ribu orang dibunuh dan jutaan lainnya ditahan tanpa proses hukum, menjadi fondasi kekuasaannya. Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Namun hingga hari ini, tak satu pun dari pelaku utama atau penanggung jawab struktural diproses secara hukum.
Lalu ada penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi menjelang kejatuhan rezim, penembakan misterius terhadap preman jalanan, represi terhadap pers dan oposisi, serta kekerasan sistemik terhadap masyarakat adat, minoritas agama, dan kaum miskin kota selama Orde Baru berlangsung. Tidak kalah penting, praktik korupsi yang terstruktur dan melibatkan kroni kekuasaan telah menjarah kekayaan negara.
Transparency International bahkan menempatkan Soeharto sebagai kepala negara paling korup di dunia berdasarkan besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam iklim seperti itu, pertanyaan moral tak bisa dielakkan: apakah seorang pemimpin yang kekuasaannya dibangun di atas kekerasan, pembungkaman, dan korupsi layak mendapatkan gelar pahlawan? Atau justru bangsa ini sedang mengalami apa yang disebut Avishai Margalit sebagai ethics of memory yang cacat, yakni ingatan kolektif yang dikonstruksi demi kenyamanan kekuasaan, bukan demi kebenaran dan keadilan?
Sejarah bukanlah catatan netral yang tinggal ditulis, melainkan arena politik. Siapa yang dikenang dan siapa yang dilupakan mencerminkan siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan makna masa lalu. Dalam hal ini, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan menandakan upaya rekonstruksi sejarah yang mengaburkan luka dan trauma kolektif demi citra stabilitas nasional. Inilah yang disebut Paul Ricoeur sebagai abuse of memory atau penyalahgunaan ingatan yang digunakan bukan untuk mengingat, melainkan untuk menghapus dan mengganti.
Sebagian akan berdalih bahwa tokoh mana pun tak ada yang sempurna, dan semua pahlawan punya sisi gelap. Argumen ini tidak keliru. Namun dalam praktiknya, setiap bangsa tetap menetapkan batas etik tentang siapa yang layak diberi tempat di ruang kehormatan nasional. Kita tidak melihat negara seperti Jerman menganugerahkan gelar kehormatan kepada para tokoh Nazi, meski sebagian di antaranya sempat membangun infrastruktur atau mengatur administrasi negara secara efisien.
Argentina tidak memberi gelar pahlawan kepada para jenderal diktator militer. Filipina tidak menempatkan Ferdinand Marcos sebagai pahlawan, justru ada gerakan rakyat besar-besaran untuk menolak jasadnya dimakamkan di Libingan ng mga Bayani. Lalu mengapa Indonesia justru cenderung permisif dalam hal ini? Apakah ini tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh berdamai dengan masa lalu, atau justru karena luka sejarah telah dijinakkan menjadi semacam kenangan bisu yang tidak lagi dianggap penting?
Atau barangkali kita tengah menyaksikan gejala apa yang disebut historical revisionism, yakni upaya merombak narasi sejarah dengan logika politik hari ini, bukan demi kebenaran, melainkan demi konsensus palsu? Gelar pahlawan seharusnya menjadi ajang afirmasi nilai-nilai luhur bangsa: kejujuran, keberanian moral, pengorbanan untuk rakyat, dan pembelaan terhadap martabat manusia. Jika nilai-nilai ini dikompromikan demi “kerukunan”, maka kita justru sedang menjual masa depan bangsa hanya demi kenyamanan sesaat.
Generasi muda berhak mendapatkan teladan sejarah yang utuh, bukan sejarah yang dimanipulasi oleh keperluan rekonsiliasi semu. Tentu kita bisa bicara rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi yang sejati hanya bisa lahir dari pengakuan dan pemulihan. Kita tidak bisa menyembuhkan luka jika kita bahkan tak bersedia mengakui bahwa luka itu ada. Maka langkah pertama yang seharusnya dilakukan negara bukanlah mengusulkan gelar kehormatan, melainkan mengakui kesalahan masa lalu secara resmi, membuka dokumen negara, meminta maaf kepada para korban dan keluarga, serta memberi ruang keadilan bagi mereka yang selama ini dikubur dalam diam. Baru setelah itu, kita bisa bicara soal pemaafan atau penghormatan.
Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan sebelum semua itu terjadi sama saja dengan membungkam suara korban untuk kedua kalinya. Ia menjadi tanda bahwa negara tidak berpihak pada keadilan, melainkan pada stabilitas politik yang dibangun di atas amnesia kolektif. Sebuah bangsa yang sehat harus bisa membedakan antara menghargai jasa dan mengafirmasi nilai. Tanpa kejelasan nilai, penghargaan bisa menjadi banal dan kehilangan makna.
Pertanyaan “pahlawan untuk siapa?” menjadi sangat relevan di sini. Apakah gelar ini diberikan untuk menenangkan elite politik dan militer yang ingin menutup masa lalu? Apakah gelar ini untuk meredam tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM yang makin tak terdengar? Atau barangkali gelar ini diberikan karena bangsa ini sudah terlalu letih untuk mengingat, dan lebih memilih berdamai dengan kepalsuan daripada menghadapi kebenaran yang menyakitkan?
Pemberian gelar pahlawan nasional seharusnya bukan hanya soal mengenang, tapi juga tentang menyampaikan pesan moral lintas generasi. Ini bukan sekadar soal nama yang dipahat di prasasti, tapi tentang warisan nilai yang akan diteladani. Maka, jika kita abai dalam menentukan siapa yang pantas diberi gelar itu, kita pun sedang menentukan siapa yang akan kita jadikan cermin bagi anak cucu kita. Dan jika cermin itu retak oleh kompromi dan kepentingan, maka bangsa ini sedang melangkah menuju masa depan dengan wajah sejarah yang kabur.