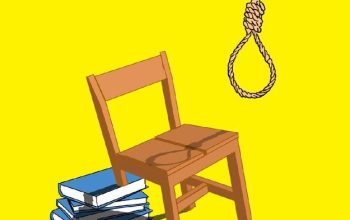Oleh: Mokhamad Abdul Aziz, Ketua Umum HMI Komisariat Dakwah Walisongo Semarang 2013-2014
Tergelitik membaca tulisan berjudul “Yang Tumbuh dari Bawah adalah PMII, Bukan HMI” di laman resmi PMII. Sekilas tampak ingin menawarkan narasi tandingan yang cerdas dan mencerahkan. Tapi semakin dibaca, tulisan itu malah terasa seperti seseorang yang sangat serius ingin meyakinkan dunia bahwa bumi itu datar—menghibur, tapi juga membingungkan.
Oh, dan tentu saja kita tidak boleh lupa: pernyataan “kalau ada yang tidak tumbuh dari bawah pasti bukan PMII, pasti itu HMI” sejatinya berasal dari Muhaimin Iskandar alias Cak Imin—tokoh politik yang sangat aktif dalam lalu lintas elite nasional, dan tidak pernah jauh dari panggung kekuasaan. Ironisnya, pernyataan tentang “tumbuh dari bawah” justru keluar dari mulut salah satu politisi paling senior yang kariernya bertahun-tahun berkubang di jantung oligarki partai. Entah itu satire kelas berat, sindiran tanpa sadar terhadap dirinya sendiri, atau malahan curhatan terselubung. Sebab sulit membayangkan seseorang yang begitu dekat dengan orbit kekuasaan tiba-tiba berbicara tentang “akar rumput” tanpa membuat penonton geleng-geleng kepala.
Guyonan semacam ini sejatinya bukan hal baru. Bahkan Gus Dur sendiri pernah berseloroh, “Kalau HMI itu menghalalkan segala cara, PMII itu malah nggak tahu caranya.” Kalimat ini tentu bukan kutukan ideologis, tapi satire khas Gus Dur—yang justru menunjukkan dinamika, kecerdasan taktis, dan kelucuan yang hidup dalam dunia aktivisme mahasiswa. Siapa yang tersinggung, mungkin belum cukup akrab dengan tradisi guyon intelektual Nusantara.
Mari kita bahas dengan secangkir kopi harapan dan keripik humor secukupnya.
Kembali fokus ke narasi, tentu saja maksudnya ada menjelaskan dan mendukung pernyataan Cak Imin, tetapi penulis artikel itu tampaknya terlalu bersemangat menegaskan bahwa PMII lebih “tumbuh dari bawah” dibanding HMI. Barangkali lupa, bahwa HMI lahir bukan dari menara gading, tetapi dari gubuk perjuangan sebuah bangsa yang baru merdeka. Saat itu, 5 Februari 1947, Indonesia bahkan belum selesai bernegara. HMI muncul sebagai bentuk keresahan intelektual anak-anak muda muslim terhadap masa depan Islam dan keindonesiaan. Bayangkan, mereka memilih berpikir strategis tentang masa depan, ketika peluru masih berseliweran di udara. Apakah itu bukan “tumbuh dari bawah”?
Oh, maaf. Mungkin yang dimaksud “bawah” adalah “gerakan bawah tanah”? Atau “di bawah komando struktural ormas”? Silakan didefinisikan ulang.
Tulisan dukungan atas pernyataan Cak Imin tersebut mencoba mengkontraskan HMI yang katanya “elitis” dengan PMII yang “membumi”. Klaim ini sayangnya lebih berbasis rasa daripada riset. Sebab, realitas menunjukkan HMI justru memiliki keanggotaan paling majemuk, tersebar dari kampus negeri, swasta, hingga pelosok-pelosok. HMI tidak menempel pada satu arus ideologi formal tertentu, justru karena otonominya yang tinggi dan kemampuan adaptasinya yang canggih. Dari dari NU, Muhammadiyah, hingga Persis, dari pesantren sampai kampus teknik, dari mahasiswa FKIP sampai teknik elektro, semua bisa jadi kader HMI.
Apa itu bukan “tumbuh dari bawah”? Atau mungkin karena tidak di-branding dengan jargon “islami-progresif-revolusioner”, lalu dianggap tidak revolusioner?
Dan mengenai “independen dari partai politik”—mohon maaf, siapa yang tidak tahu bahwa hampir semua organisasi mahasiswa punya sejarah dan jejak politis masing-masing? HMI jelas punya orang-orang yang nyambung ke banyak partai. Tapi yang membedakan, HMI tidak pernah menjadi satelit. Kadernya justru menyusup di berbagai spektrum ideologi: dari nasionalis, Islamis, hingga liberal—itulah bukti kedewasaan gerakan, bukan inkonsistensi. Kalau ada kader HMI yang jadi menteri, aktivis HAM, pengusaha, atau bahkan oposisi garis keras—itu bukan karena dia tidak punya garis ideologi. Itu karena ia bewawasan politik, bertindak strategis-taktis, dan memilih jalannya sendiri.
Kalau ingin bicara keragaman latar belakang, HMI bahkan tidak pernah tertutup untuk siapa pun—termasuk dari kalangan Nahdliyin. Fakta yang tak terbantahkan: Ketua Umum PBNU saat ini, KH. Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Umumnya, H. Saifullah Yusuf, sama-sama pernah menjadi kader HMI. Apakah ini membuat mereka kurang “NU”? Tentu tidak. Justru di situ terlihat kedewasaan: bahwa HMI bukan ruang asuhan dogmatis, melainkan kawah candradimuka kaum muda Islam untuk berpikir, bergerak, dan memperluas cakrawala.
Bandingkan dengan yang lebih bangga “menegaskan garis warisan”, tapi kemudian tidak banyak menghasilkan lompatan.
Kalau ingin bicara warisan, mari ukur juga kontribusi. HMI telah melahirkan wakil presiden, menteri berbagai bidang, kepala daerah, tokoh pergerakan, intelektual-ilmuwan, penulis, guru, bahkan pemimpin ormas terbesar. Jadi, pertanyaannya sederhana, siapa yang benar-benar berakar ke rakyat—yang sekadar bicara “dari bawah”, atau yang benar-benar membentuk wajah Indonesia dari bawah, tengah, dan atas sekaligus?
Memang, dalam dinamika sejarah, setiap organisasi punya masanya sendiri untuk mengukir peran. Tapi menulis sejarah sambil menghapus peran orang lain, itu bukan narasi tandingan. Itu namanya amnesia dengan gaya literer.
Dan kalau memang ingin adu kontribusi, mari kita dudukkan data dan karya. Kalau sekadar saling sebut “kami lebih membumi” atau “kami lebih orisinal”—jangan-jangan kita sedang main layangan di tengah forum ilmiah.
Tentu saja, jika keberhasilan kader HMI duduk di kursi-kursi strategis dianggap “dosa sejarah,” maka bangsa ini sedang mengalami alergi terhadap keberhasilan anak muda berotak tajam yang berani bermain di gelanggang elite. Aneh memang. Ketika kader HMI jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi duta besar, bahkan ketua partai—itu dianggap terlalu “elit.” Tapi ketika jadi korban PHK atau jadi aktivis jalanan yang hidup dari satu proyek ke proyek lain, barulah mereka dipuji “merakyat.” Lucu, bukan?
Fakta bahwa kader HMI berseliweran di pusat-pusat kekuasaan justru menjadi bukti bahwa mereka paham cara kerja negara ini. Mereka tidak sibuk mengeluh di pinggir lapangan sejarah sambil memaki “para elit,” tapi memilih masuk ke dalam sistem untuk ikut menentukan arah permainan. Mereka berdamai dengan kenyataan bahwa idealisme tanpa akses pada kekuasaan hanya akan menjadi puisi tanpa pembaca.
HMI tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa kader-kadernya ada di orbit kekuasaan. Justru di sanalah tempat di mana banyak keputusan strategis bangsa diambil. Yang tidak mau ke sana silakan tetap beternak wacana di kampus, berdialog dengan bayangan sendiri, atau sibuk mengkritik sambil ngopi di angkringan. HMI memilih jalan terjal, bukan sekadar menuntut perubahan tapi turut menulisnya.
Dalam hal strategi perubahan, HMI juga tidak kaku seperti kaum revolusioner puritan yang percaya bahwa satu-satunya cara mengubah dunia adalah dengan demo dan poster. HMI paham benar bahwa kadang perubahan justru datang dari istana, dari ruang kabinet, dari meja-meja rapat. Itulah yang disebut revolusi dari atas. Tapi bukan berarti mereka meninggalkan perbaikan dari pinggir—karena di saat yang sama, kader HMI juga mendirikan sekolah, menggerakkan komunitas, menghidupkan masjid, dan memajukan desa. Mereka tidak sibuk memilih satu cara—mereka lakukan semua cara.
Sudah jadi pemandangan lazim di negeri ini, yang orasi lantang di jalan pakai atribut HMI, yang menerima audiensi di balik meja kekuasaan juga mantan Ketua Umum HMI. Kadang, yang didemo dan yang demo sama-sama ngaji bareng dulu di Basic Training. Lucunya, mereka tetap bisa ngopi bareng setelah debat panas. Inilah politik ala HMI: penuh dialektika, tapi tidak kehilangan etika. Jadi kalau ada yang heran kenapa HMI seperti ada di mana-mana, jawabannya sederhana—karena mereka memang tumbuh bersama dinamika bangsa, bukan sekadar bersembunyi di balik romantisme pinggir jalan.
Jadi, jika ada yang masih sibuk memisah-misahkan antara akar rumput dan puncak menara, antara rakyat dan elit, antara pinggiran dan pusat, maka izinkan HMI memberi satu kalimat pendek: “Selamat datang di dunia nyata.”
Akhir kata, bagi HMI, debat semacam ini ibarat nostalgia. Tidak semua harus ditanggapi serius. Tapi kalau ada yang mulai menulis sejarah dengan cara menghapus sejarah orang lain—ya, kadang perlu disolek balik. Dengan catatan kaki. Dan senyuman sinis. Walláhu a’lam bi al-shawwáb.