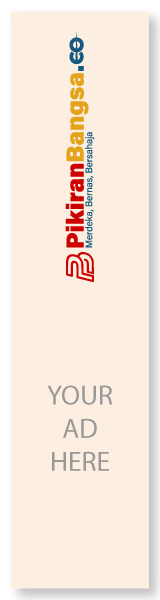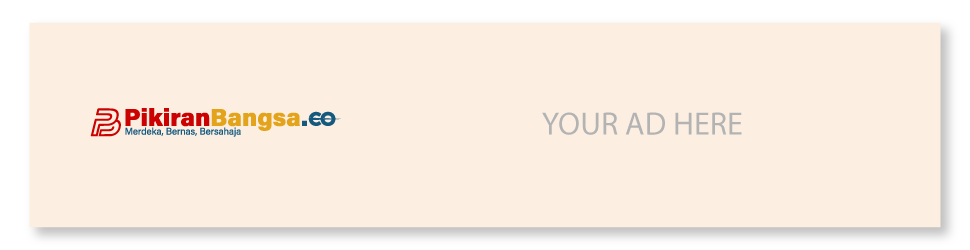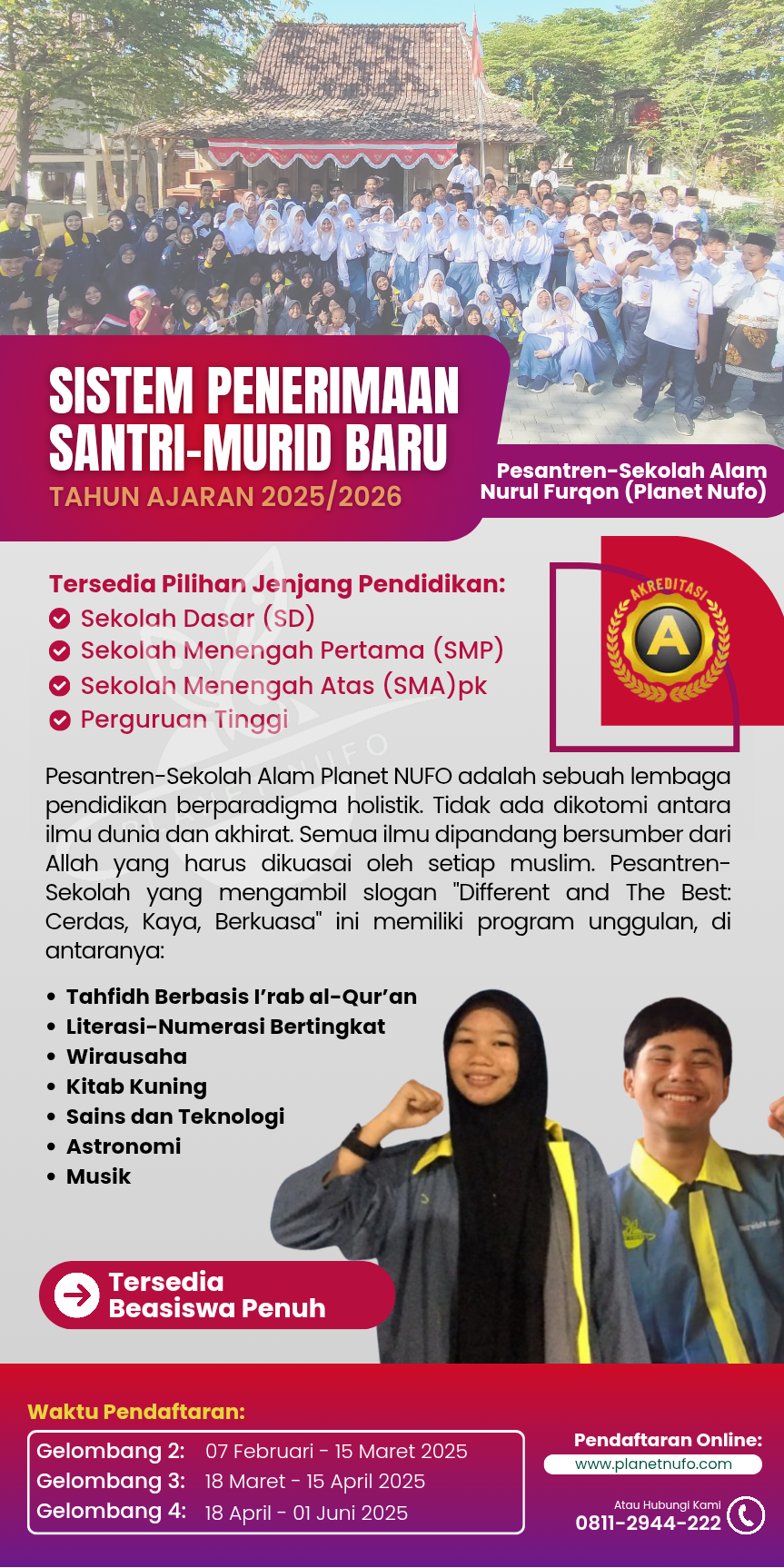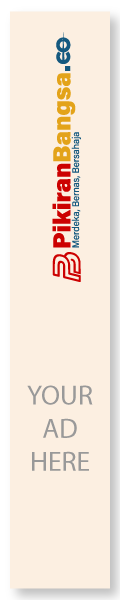Oleh: Aqibul Muttaqin, Ketua umum HMI Komisariat Ki Hadjar Dewantara, Cabang Pekalongan
Berabad-abad sebelum sistem pendidikan modern hadir lewat kebijakan kolonial, masyarakat Nusantara sudah memiliki bentuk pendidikan yang lahir dari kebijaksanaan lokal: pesantren. Ia bukan hasil pinjaman dari luar, bukan pula tiruan dari dunia Barat. Pesantren tumbuh dari denyut kehidupan desa, dari tradisi Islam yang berakar dalam tanah air sendiri. Ia hidup di tengah masyarakat, menjadi bagian dari mereka, bukan entitas yang berdiri di luar.
Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Azyumardi Azra dalam Bilik-bilik Pesantren, lembaga ini merupakan bentuk pendidikan “indigenous” (lahir dari rahim masyarakat) bukan hasil adopsi. Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, melainkan juga cermin kehidupan sosial dan spiritual masyarakat di sekitarnya. Ia bukan menara gading, melainkan rumah bersama bagi pencarian ilmu dan pengabdian.
Hal yang serupa juga ditegaskan oleh Nurcholish Madjid. Bagi Cak Nur, pesantren memegang peranan penting dalam perjalanan bangsa. Ia menyebutnya sebagai lembaga yang tumbuh dari aspirasi masyarakat sendiri, memiliki daya hidup yang lentur namun kokoh. Jika Indonesia ingin membangun peradaban yang berpijak pada akar budaya sendiri, pesantrenlah yang paling mungkin menjadi pondasinya. Di sanalah terbentuk nilai-nilai luhur: keikhlasan, kesederhanaan, dan keteguhan moral.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), melangkah lebih jauh dengan menyebut pesantren sebagai sebuah subkultur. Ia menggambarkan pesantren sebagai dunia kecil yang memiliki sistem sosial, kepemimpinan, dan tata nilainya sendiri. Kiai bukan hanya pengajar, melainkan poros moral; santri bukan sekadar murid, melainkan bagian dari komunitas yang diikat oleh cinta dan hormat. Di dalamnya hidup etika, spiritualitas, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi.
Namun seperti semua hal yang hidup, pesantren juga menghadapi masa-masa ujian.Di Balik Citra dan LukaDalam dunia yang serba terbuka hari ini, pesantren tak lagi berdiri di ruang sunyi. Sorotan publik kini menembus dinding-dinding bilik dan pagar bambu. Dan sayangnya, beberapa peristiwa kelam mencoreng wajah suci lembaga ini, kasus kekerasan seksual, perundungan, hingga penyalahgunaan otoritas moral oleh segelintir oknum. Luka itu terasa dalam; lebih dari sekadar berita, ia mengguncang rasa percaya masyarakat.
Data dari PPIM UIN Jakarta menunjukkan, lebih dari 43 ribu santri berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan seksual. Laporan JPPI pun mencatat, satu dari lima kasus kekerasan di dunia pendidikan terjadi di lingkungan pesantren. Tahun 2024 bahkan disebut sebagai tahun paling gelap dalam catatan mereka, lonjakan kasus meningkat dua kali lipat dari sebelumnya.Pertanyaan pun muncul dengan getir: bagaimana bisa lembaga yang selama ini menjadi benteng moral justru lalai menjaga keselamatan anak didiknya?
Cak Nur sebenarnya sudah mengingatkan jauh hari sebelumnya. Dalam banyak tulisannya, ia menegaskan bahwa ancaman terbesar bagi pesantren bukan datang dari luar, melainkan dari dalam: kehilangan arah. Banyak pesantren masih berputar di sekitar figur kiai, tanpa sistem kelembagaan yang matang. Padahal, dunia modern menuntut transparansi, sistem, dan rasionalitas, sesuatu yang belum sepenuhnya dikelola oleh banyak pesantren hari ini.
Seandainya Indonesia tidak pernah dijajah, tulis Cak Nur, mungkin sistem pendidikan nasional akan bertumbuh mengikuti pola pesantren. Barangkali, yang kita kenal kini bukan Universitas Indonesia atau ITB, melainkan Universitas Tebuireng atau Tremas. Karena di Barat pun, lembaga besar seperti Harvard dan Oxford lahir dari lembaga keagamaan. Pertanyaannya: mengapa pesantren tidak bisa menempuh jalan yang sama? Jawabannya mungkin terletak pada satu hal: pesantren sering gagap menghadapi dunia modern, karena terlalu berhati-hati meninggalkan masa lalunya.
Di Simpang Jalan Modernitas
Meski begitu, ujian bukan alasan untuk menyerah. Pesantren justru diuji agar menemukan kembali daya hidupnya. Gus Dur menyebut proses itu sebagai dinamisasi: menghidupkan nilai lama yang masih relevan, sekaligus memperbarui yang telah usang. Modernisasi bukan sekadar meniru Barat, tapi memperbarui diri berdasarkan kekuatan sendiri. Inilah bentuk ijtihad kelembagaan yang seharusnya dijalankan pesantren.Tradisi yang hidup di pesantren tidak pernah statis; ia selalu tumbuh mengikuti zaman. Karena itu, pembaruan sejati hanya bisa lahir dari dalam—bukan dari tekanan luar. Perubahan yang dipaksakan sering menimbulkan perlawanan, tetapi perubahan yang tumbuh dari kesadaran akan melahirkan keberlanjutan.
Pesantren hari ini perlu membuka jendela bagi dunia luar, tanpa harus menanggalkan jubah tradisinya. Santri perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, pengetahuan umum, dan teknologi, namun tetap berakar pada nilai-nilai spiritual. Ilmu agama tidak boleh berhenti pada hafalan, tapi harus berkembang menjadi pandangan hidup yang menyeluruh, weltanschauung Islam, kata Cak Nur.
Muhasabah dan HarapanKini, kita sampai pada titik muhasabah. Apakah pesantren mampu tetap menjadi sumber cahaya di tengah dunia yang berubah cepat ini? Atau justru perlahan kehilangan sinarnya, menjadi sekadar peninggalan masa lalu, seperti yang pernah diingatkan Ivan Aulia Ahsan—fosil peradaban yang hanya dikunjungi untuk nostalgia?
Sebagai seseorang yang pernah bertahun-tahun hidup di pesantren, saya percaya: pesantren tidak akan hilang. Ia telah melalui beragam zaman; kolonialisme, reformasi, bahkan era digital. Dan setiap kali diterpa badai, ia selalu menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Kadang dengan diam, kadang dengan perubahan yang perlahan, tapi pasti.
Dulu pesantren menjadi benteng melawan penjajahan; kini ia harus menjadi benteng melawan kebodohan, ketimpangan, dan dekadensi moral. Nilai lama seperti ikhlas, sabar, dan zuhud perlu diterjemahkan kembali dalam bentuk baru: etos kerja, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.Seperti kata Gus Dur, perubahan bukan berarti mengkhianati tradisi, tapi menyempurnakannya. Dan seperti pesan Cak Nur, modernisasi sejati adalah pembaruan dari dalam, bukan meniru, tapi menemukan kembali.
Hari Santri bukan sekadar peringatan sejarah. Ia adalah undangan untuk menunduk, bermuhasabah, dan bertanya kepada diri sendiri: sudah sejauh mana pesantren ikut menerangi bangsa?Pesantren harus terus hidup, bukan sebagai fosil, tapi sebagai pelita masa depan.Selamat Hari Santri Nasional 2025.Semoga pesantren tetap menjadi sumber ilmu, cahaya, dan cinta bagi peradaban manusia.