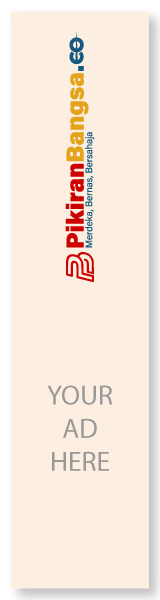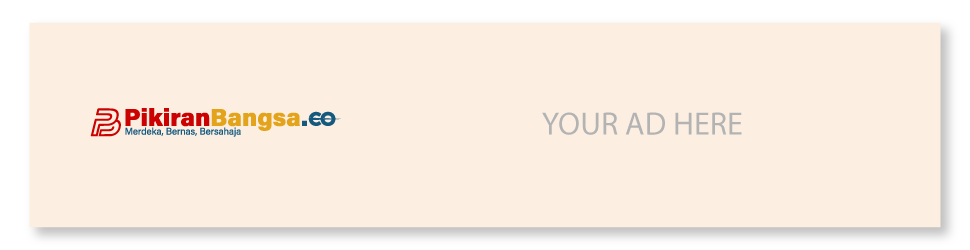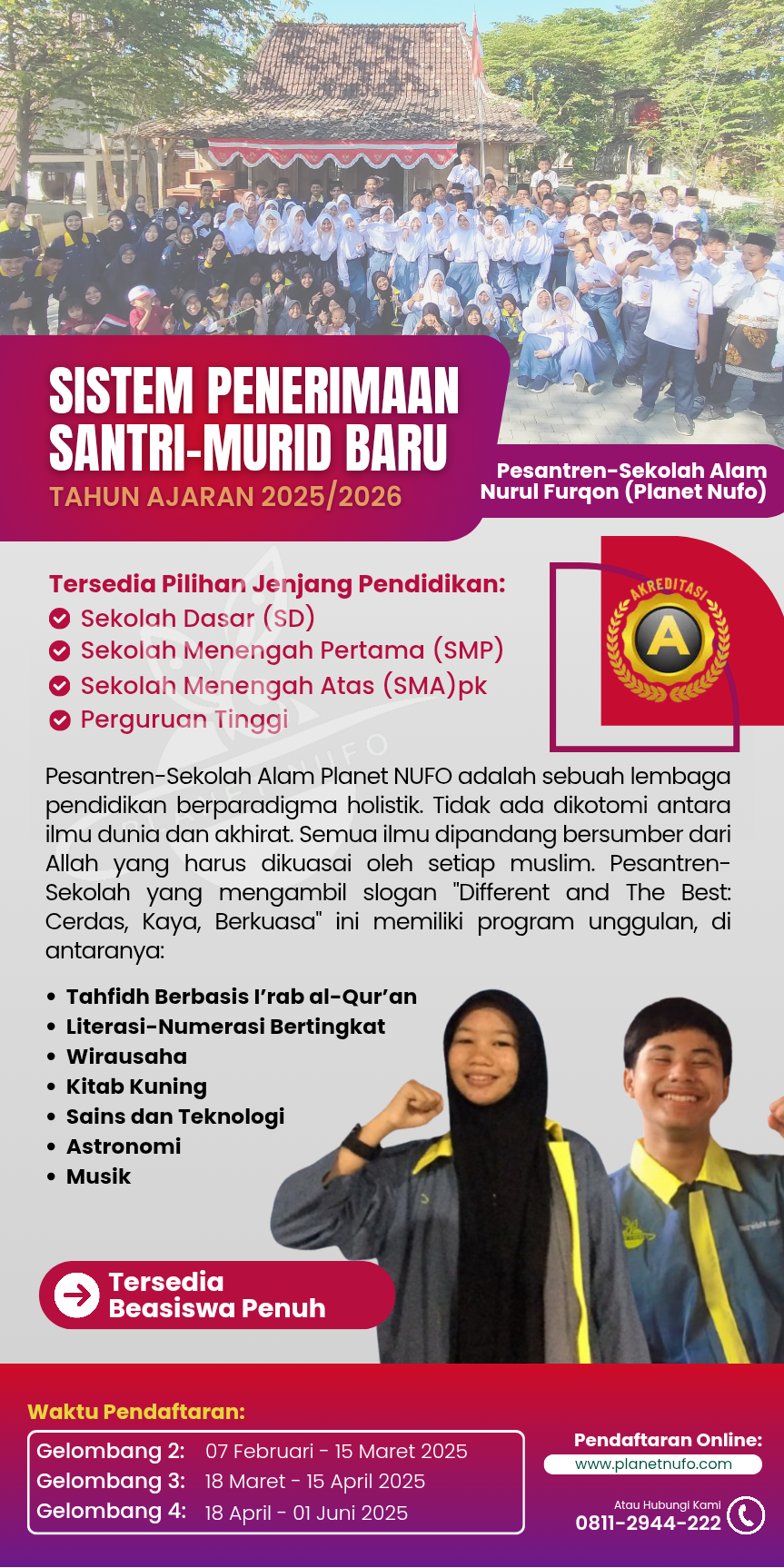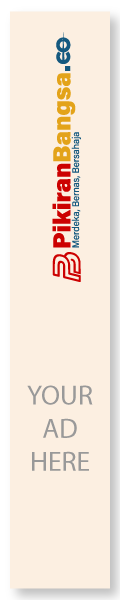Oleh: Indah Nur Fadlillah, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Pemilu atau pesta demokrasi bukan sekadar momentum lima tahunan yang berisi rutinitas memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Lebih dari itu, pemilu adalah cermin kedewasaan politik sebuah bangsa. Ia menjadi medan di mana rakyat tidak hanya diberikan hak, tetapi juga ditantang untuk bertanggung jawab terhadap masa depan negara. Saat ini, publik Indonesia tengah dihadapkan pada dua tantangan utama dalam konteks pemilu mendatang, yaitu politics of money dan hoaks masif. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bahkan menyebut kedua masalah ini sebagai “musuh utama demokrasi” dalam penyelenggaraan pemilu 2025 (kompas.com).
Di sisi lain, masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat adanya 1.292 hoaks politik sepanjang tahun 2023 dua kali lipat dibanding periode 2019 sebagai dampak dari gejala disinformasi yang mengganas jelang pemilu (mafindo.or.id). Tidak hanya itu, polarisasi di dunia maya juga memecah kerukunan sosial, terbukti dari analisis Bawaslu yang menemukan bahwa unggahan provokatif di media sosial menjadi pemicu utama polarisasi masyarakat menjelang Pilpres 2024. Oleh karena itu, dalam menghadapi pemilu mendatang, dibutuhkan sebuah persiapan yang tidak sekadar administratif atau teknis, melainkan menyeluruhpersiapan yang bersifat multidimensional.
Pertama, dimensi literasi politik menjadi fondasi utama. Masih banyak masyarakat yang memahami politik sebatas pada soal siapa yang akan menang atau siapa yang ‘bagi-bagi sembako’. Demokrasi kemudian terjebak dalam romantisme elektoral tanpa pemahaman esensial mengenai fungsi kekuasaan, peran legislatif dan eksekutif, serta bagaimana kebijakan publik seharusnya dikawal. Literasi politik bukan hanya penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi, tetapi juga untuk mencegah masyarakat dari jebakan politisasi agama, hoaks, hingga politik uang yang masih mengakar kuat di berbagai daerah.
Upaya literasi ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Bukan hanya menjelang pemilu, tetapi sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang hidup dalam ruang-ruang publik—baik melalui media sosial, forum diskusi kampus, hingga pengajian atau kelompok masyarakat di tingkat akar rumput. Kaum muda dan intelektual, termasuk mahasiswa, harus menjadi lokomotif gerakan ini. Mereka memiliki peran strategis dalam mendistribusikan pemahaman politik yang sehat, terbuka, dan partisipatif.
Kedua, aspek etik dan integritas dalam politik perlu menjadi bagian dari persiapan kita bersama. Dalam banyak kasus, masyarakat sering kali bersikap permisif terhadap praktik politik yang tidak etis karena merasa tidak punya pilihan. Padahal, integritas bukan hanya tanggung jawab elite politik, tetapi juga pemilih. Kita perlu membangun budaya politik yang tidak hanya bertumpu pada popularitas atau elektabilitas, tetapi juga pada rekam jejak, kapabilitas, serta komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
Pendidikan etika ini bisa dimulai dari hal kecil, seperti tidak menyebarkan ujaran kebencian saat kampanye, menghindari fanatisme buta terhadap tokoh tertentu, dan terbiasa menguji kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya. Etika politik seharusnya menjadi kesadaran kolektif, bukan hanya urusan para kandidat.
Ketiga, persiapan teknis dan kelembagaan juga tidak bisa diabaikan. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu memegang tanggung jawab besar untuk memastikan proses berjalan jujur, adil, dan transparan. Ini mencakup kesiapan logistik, pemutakhiran data pemilih, pelatihan petugas lapangan, serta sistem pengawasan yang kuat. Kelemahan di sisi teknis kerap menjadi celah bagi kecurangan yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu.
Namun, lebih dari sekadar profesionalisme teknis, integritas kelembagaan penyelenggara pemilu harus terus dijaga. Kepercayaan publik terhadap netralitas KPU, Bawaslu, dan aparat negara menjadi modal penting agar hasil pemilu diterima semua pihak dan tidak menimbulkan konflik horizontal.
Keempat, dimensi sosial dan psikologis masyarakat pun perlu menjadi perhatian. Pemilu kerap menjadi ajang polarisasi, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Kita menyaksikan bagaimana perbedaan pilihan politik dapat merusak hubungan kekeluargaan, pertemanan, bahkan kohesi sosial. Oleh sebab itu, perlu ada upaya membangun budaya demokrasi yang dewasa—yang mampu menghargai perbedaan, berdialog dengan sehat, serta memisahkan antara kritik terhadap pilihan politik dengan serangan terhadap identitas personal.
Media sosial sebagai ruang kontestasi opini publik harus diarahkan menjadi arena yang konstruktif. Pemerintah, aktivis, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk memerangi disinformasi dan ujaran kebencian, serta mendorong kampanye politik yang cerdas, beradab, dan berorientasi pada program, bukan sekadar personalisasi tokoh.
Kelima, dimensi ekonomi juga memiliki peran tidak kecil. Kemiskinan struktural yang masih membelenggu sebagian masyarakat membuat mereka rentan terhadap politik transaksional. Maka, upaya membangun demokrasi yang sehat juga harus dibarengi dengan agenda pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif. Kemandirian ekonomi rakyat menjadi benteng yang efektif dalam menolak praktik politik uang.
Pesta demokrasi mendatang seharusnya tidak kita hadapi dengan gegap gempita sesaat, tetapi dengan kesiapan yang matang dan mendalam. Literasi politik, integritas, kesiapan teknis, kedewasaan sosial, serta kemandirian ekonomi semuanya saling berkaitan dan memperkuat. Dengan pendekatan yang multidimensional, kita tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga sedang menanam masa depan demokrasi Indonesia yang lebih matang dan beradab. Wa Allahu a’lam bi al-shawab.