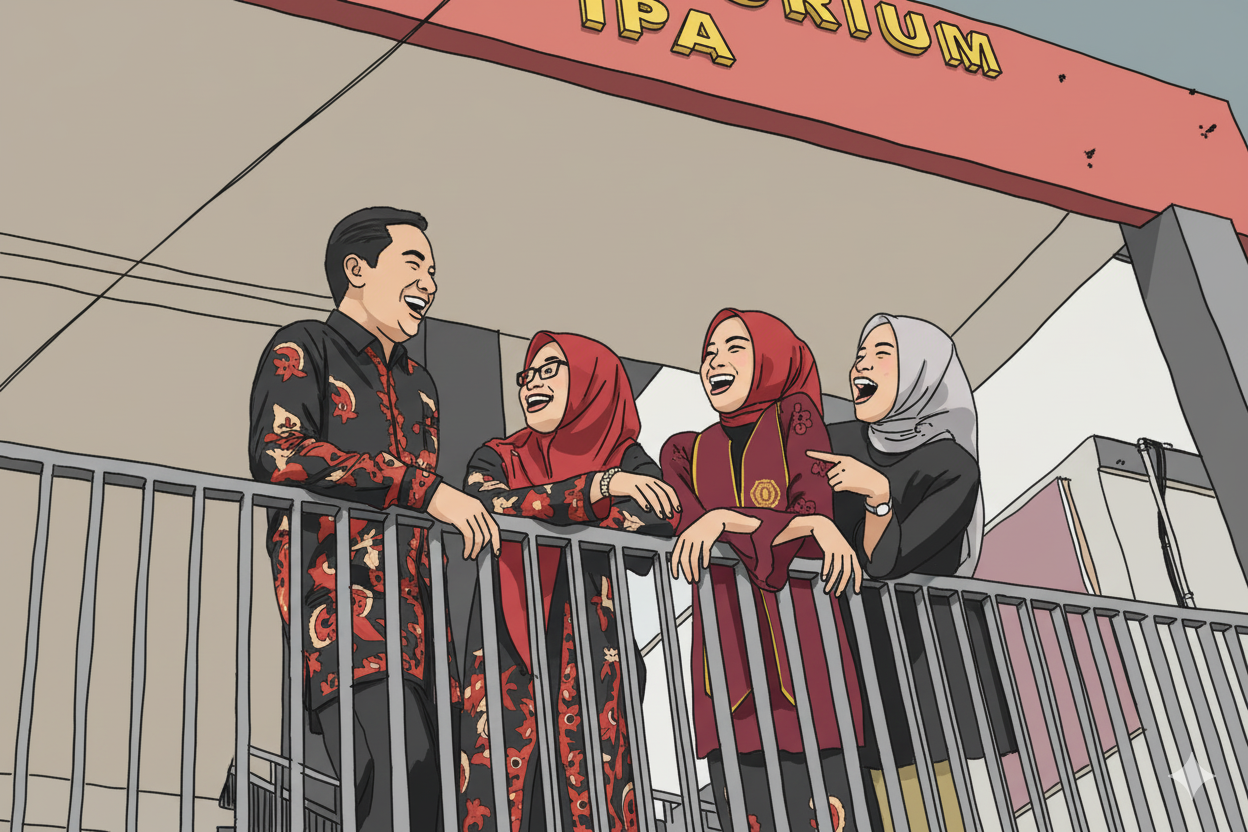Oleh: Rajni Argianti Firzatulloh, Mahasiswa FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
“Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu gemeter, takut, berarti mimpinya belum cukup besar.”
Kalimat itu ia dengar dari podcast Mbak Najwa Shihab, ditemani cahaya senja yang menembus celah jendela kamar kecilnya. Entah kenapa, kalimat itu terasa menampar, seolah diucapkan langsung untuknya—anak seorang buruh tani yang punya mimpi setinggi langit.
Namanya Dira, anak seorang buruh tani dari sebuah desa kecil yang nyaris tak pernah muncul di peta. Ayahnya menanam padi di sawah orang, sementara ibunya mencuci pakaian tetangga demi menambah uang belanja. Di rumah kecil yang berdinding papan, Dira menanam satu impian besar: menjadi guru, dan menjadi sarjana pertama di keluarganya.
Cemooh sudah menjadi santapan sehari-hari.
“Anak petani mana bisa jadi guru? Nanti ujung-ujungnya juga balik ke sawah” kata orang-orang dnegan nada meremehkan. Ucapan itu sempat membuat dadanya sesak, tapi tak cukup kuat untuk memadamkan semangatnya. Ia percaya, nasib bisa diubah asal mau berusaha.
Dengan doa dan restu kedua orang tuanya, ia melangkah penuh keyakinan. Jalan yang ia tempuh memang tidak mudah, tapi setiap kali hatinya mulai gentar, ia selalu teringat kalimat yang paling sering diucapkan ibunya, “Doa orang tua itu seperti hujan, Nak. Turunnya mungkin pelan, tapi pasti sampai.” Kalimat sederhana, tapi baginya lebih kuat dari apa pun.
Tuhan memang pandai menulis kejutan. Suatu hari, sebuah surat datang: ia diterima di universitas negeri di kota besar. Saat membaca namanya di lembar pengumuman—sesuatu yang dulu hanya bisa ia bayangkan diam-diam. Jurusan yang ia dapat mungkin tak pernah terlintas dalam pikirannya, tapi ia menerimanya dengan hati penuh syukur. Ia tahu, tak semua orang seberuntung dirinya. Dengan air matanya pecah tanpa suara. Ia memeluk ibunya lama sekali, mencium tangan ayahnya yang kapalan, lalu berjanji dalam hati: aku tidak akan pulang sebelum mimpi ini terwujud.
Pagi keberangkatannya begitu cerah. Burung-burung beterbangan di atas sawah yang berembun. Ibunya menyelipkan uang dua ratus ribu di saku bajunya sambil berkata “Ini Cuma sedikit, Nak. Tapi doa ibu banyak”. Dira hanya mengangguk, menahan air mata yang mulai menggenang. Dari jendela bus, ia menatap sawah yang perlahan mengecil di kejauhan. Desa itu tak lagi hanya tempat ia tumbuh—ia tinggalkan di sana sepotong dirinya sendiri.
Hari-harinya di tanah rantau dimulai dengan rasa harap, cemas, dan rindu yang tak pernah hiking. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, jauh dari keluarga dan orang tua yang selalu ia jadikan tempat bersandar. Setiap kali ia menelpon orang dirumah, suara ibunya terdengar hangat tapi mulai pelan, rambut ayahnya semakin memutih. Ada rasa takut dalam dirinya—takut kalua waktu berjalan terlalu cepat, sementara ia masih berjuang mengerjar mimpinya yang terasa begitu jauh.
Menjadi mahasiswa ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tugas datang silih berganti, menumpuk seperti baju kotor yang belum dicuci seminggu. Deadline terasa seperti bayangan yang selalu mengintai, membuatnya sering begadang, bahkan tak tidur sama sekali. Kepala terasa penuh, tubuh Lelah, tapi semua ia tahan, Ia menutupi semua rasa capek itu dari keluarganya. Saat menelpon, ia hanya menampilkan tawa, bukan air mata. Setiap kali menelpon ke rumah, suaranya dibuat ceria. “Ibu jangan khawatir, Dira senang di sini.” Ia tak pernah bercerita bahwa ia sering menangis diam-diam, takut pada jarak dan waktu yang membuat kedua orang tuanya semakin renta. Ia hanya ingin mereka tahu, anak mereka sedang berjuang sebaik mungkin. Ia tahu, orang tuanya sudah cukup lelah mencari uang demi biaya kuliahnya. Maka sebisa mungkin ia tidak menambah beban pikiran mereka. “Cukup aku yang lelah,” begitu pikirnya, “mereka jangan”.
Di tanah rantau, ia bertemu banyak orang baru—dengan karakter, latar belakang, dan cara berpikir yang beragam. Tidak jarang ia merasa tertinggal. Saat dosen melempar pertanyaan, teman-temannya dengan mudah menjawab, sementara ia masih berusaha mencerna maksud dri pertanyaan itu. Ada rasa minder, tapi juga keinginan besar untuk terus belajar. Ia sadar, setiap orang punya waktunya masing-masing. Hanya saja, dalam diam, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, “Bisakah aku benar-benar mengejar mereka yang hampir sampai, sementara aku masih tertatih di setengah jalan?”
Sore hari menjadi waktu yang paling sering ia habiskan untuk berpikir.
Sepulang kuliah, ia duduk di bawah langit oranye yang perlahan berubah ungu, menatap matahari yang tenggelam di balik gedung kampus. Bersama cahaya senja itu, ia sering bertanya dengan dirinya sendiri. “Apa sih yang sebenarnya aku kejar di duni yang fana ini?”
Tapi kemudian, bayangan wajah ayah dan ibunya kembali muncul di kepala. Senyum mereka, kerut di wajah, dan tangan yang kasar karena kerja keras. Ia tahu jawabannya: ia tidak hanya mengejar mimpinya, tapi juga ingin menghadiahkan kebahagiaan untuk dua orang yang paling berarti dalam hidupnya.
Ia ingin suatu hari bisa berdiri di depan kelas dengan penuh percaya diri, memegang kapur putih dan menulis di papan tulis, sambil mengenang perjalanan panjang yang membawanya sampai ke titik itu. Ia ingin orang tuanya duduk di barisan paling depan saat wisuda nanti, tersenyum bangga sambil menatap anaknya yang dulu hanya seorang anak petani.
Karena baginya, keberhasilan bukan hanya tentang gelar atau pekerjaan.
Keberhasilan adalah saat ia bisa membuat orang tuanya meneteskan air mata bahagia—setelah sekian lama meneteskan keringat demi dirinya.
Dan di setiap doa yang ia panjatkan di malam hari, di kamar kecilnya di tanah rantau, ia selalu mengucapkan kalimat yang sama, “Ya Tuhan, jikalau aku lelah, jangan biarkan aku berhenti. Biarkan aku istirahat sebentar, tapi jangan izinkan aku mnyerah.”
Sebab ia tahu, di ujung jalan yang panjang ini, ada cahaya yang menunggunnya—cahaya yang berasal dari doa orang tua, dan keyakinannya sendiri bahwa anak petani pun bisa bermimpi besar. Serta mimpi yang disiram dengan doa tak akan pernah layu.
Dan barangkali, itulah cara Tuhan membalas perjuangan: bukan dengan kemewahan, tapi dengan kesempatan untuk membuat mimpi orang lain tumbuh seperti dirinya dulu—di tanah sederhana, di bawah langit yang sama, dan dengan doa yang tak pernah berhenti.