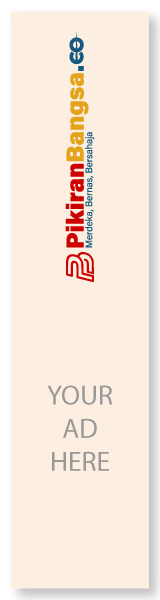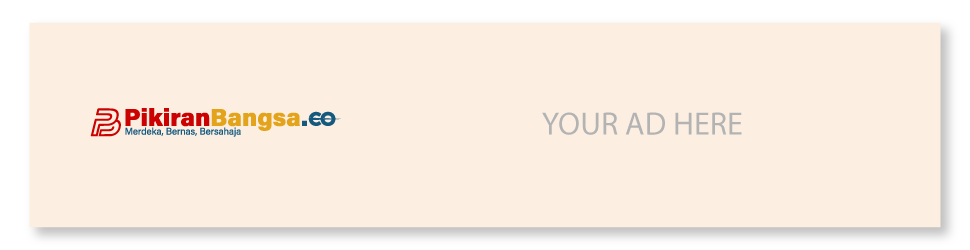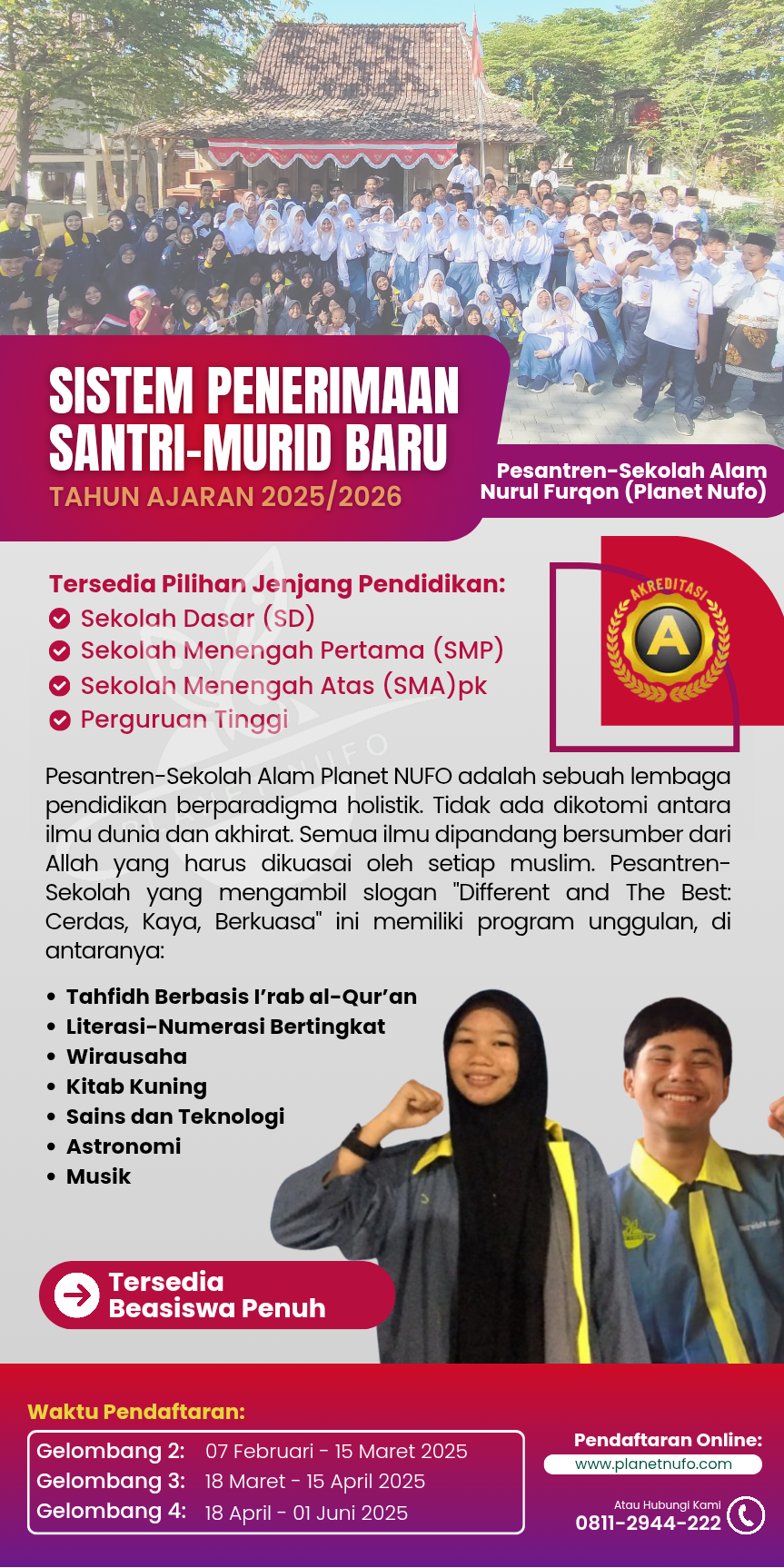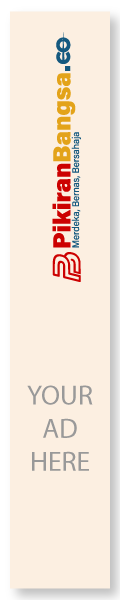Oleh: Muhammad Syaiful Reza, Mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Walisongo Semarang
Maraknya brand kecantikan dan perawatan diri yang bermunculan dekade terakhir menuntut tiap brand mengembangkan materi promosi yang ideal agar mampu bertahan dalam gelombang persaingan yang massif. Fenomena lain yang timbul bersamaan dengan fenomena tersebut adalah woke agenda yang menjangkiti banyak—untuk tidak mengatakan mayoritas—anak muda yang tergolong dalam generasi Z (yang lahir di tahun 1997-2012).
Implikasinya dalam bidang kecantikan adalah munculnya gerakan melawan sterotip dan stigma tentang tubuh ideal yang sudah ada sejak lama.
standar kecantikan yang berubah juga akhirnya membuat brand-brand berbenah. Yang dipekerjakan untuk menjadi model pakaian renang bukan lagi hanya yang berbadan langsing, namun juga yang kelebihan berat badan. Yang menjadi model untuk produk make up bukan lagi sekedar perempuan, namun juga laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga image brand tersebut sebagai brand yang mendukung inklusifitas.
Namun, gerakan body positivity muncul bukan tanpa masalah. Gerakan yang mulanya ditujukan agar setiap orang mencintai fisik sendiri, bagaimanapun keadaannya, apapun kekurangannya, justru malah menjadi toxic positivity. Contoh kasusnya adalah golongan obesitas yang karena termakan campaign body positivity tidak memperdulikan kesehatannya yang memburuk akibat berat badan berlebih.
Masalah lain yang timbul adalah objektifikasi diri yang menjadi marak. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa mereka yang fisiknya tidak sesuai standar ideal lebih jarang mendapatkan validasi sosial, sementara yang tampil dengan tubuh ‘ideal’ lebih sering dipuji dan mendapatkan engagement tinggi. Hal ini memperkuat kecenderungan objektifikasi diri, terutama pada perempuan muda, yang merasa perlu menampilkan tubuh mereka demi mendapatkan validasi sosial.
Body positivity sebagai wacana dapat dipahami dan ditafsirkan melalui kacamata Hermeneutika. Salah satu tokoh yang menyumbang pemikiran di dalamnya adalah Jurgen Habermas, seorang filosof dan sosiolog asal Jerman yang merupakan jebolan mazhab Franfurt generasi kedua. Ia berpendapat kalau untuk memahami wacana, tidak cukup hanya dengan menggali makna. Diperlukan juga analisis terhadap struktur dominasi dan relasi kuasa yang membentuk wacana tersebut. Ia menolak pendapat Gadamer yang mengedepankan pengungkapan makna melalui tradisi dan Bahasa.
Dalam konteks fenomena Body Positivity, wacana yang semula bertujuan untuk mematahkan stigma tentang kecantikan dan mendorong agar setiap orang tidak merasakan body dysmorphia lama kelamaan justru malah menjadi alat kapitalis. Standar kecantikan sebelumnya sejatinya masih dipertahankan, tapi dicitrakan sebaliknya untuk tujuan advertising (pengiklanan).
Menurut Jurgen Habermas, semakin banyak golongan yang mendapat kesempatan merepresentasikan dirinya, semakin dekat masyarakat dengan kondisi komunikasi yang ideal. Menurutnya, agar terjadi sebuah public speher (ruang publik) yang mana terjadi komunikasi antar-subjek, sehingga terjadi diskursus yang inklusif.
Dalam wacana Body positivity, semua kalangan seakan diberi ruang untuk mengekspresikan tubuhnya. Tapi ada golongan yang luput dari ruang diskusi, seperti ahli medis yang pendapatnya tentang bentuk tubuh dicap sebagai pernyataan body shaming, juga kalangan menengah ke bawah yang tidak mampu membeli produk yang mengkampanyekan bahwa produknya bisa diakses dan dipakai semua golongan.
Fenomena Body positivity tidak bisa dilihat hanya sebagai gerakan mencintai tubuh sendiri, namun dominasi kekuasaan dan kepentingan yang ada dibaliknya juga harus diperhatikan agar tercipta ruang yang benar-benar inklusif bagi semua pihak.