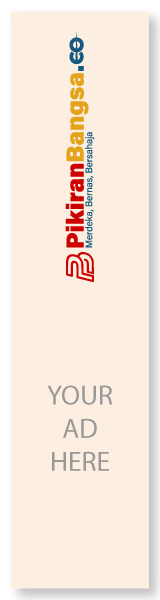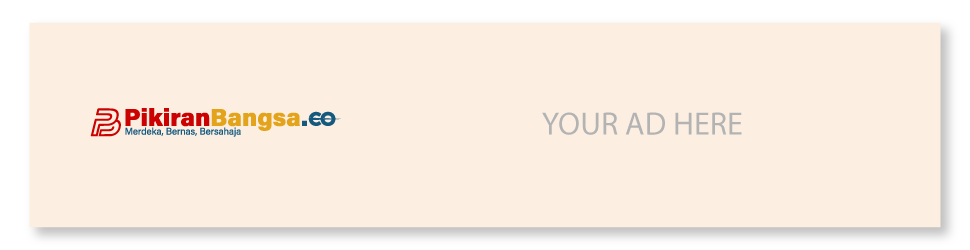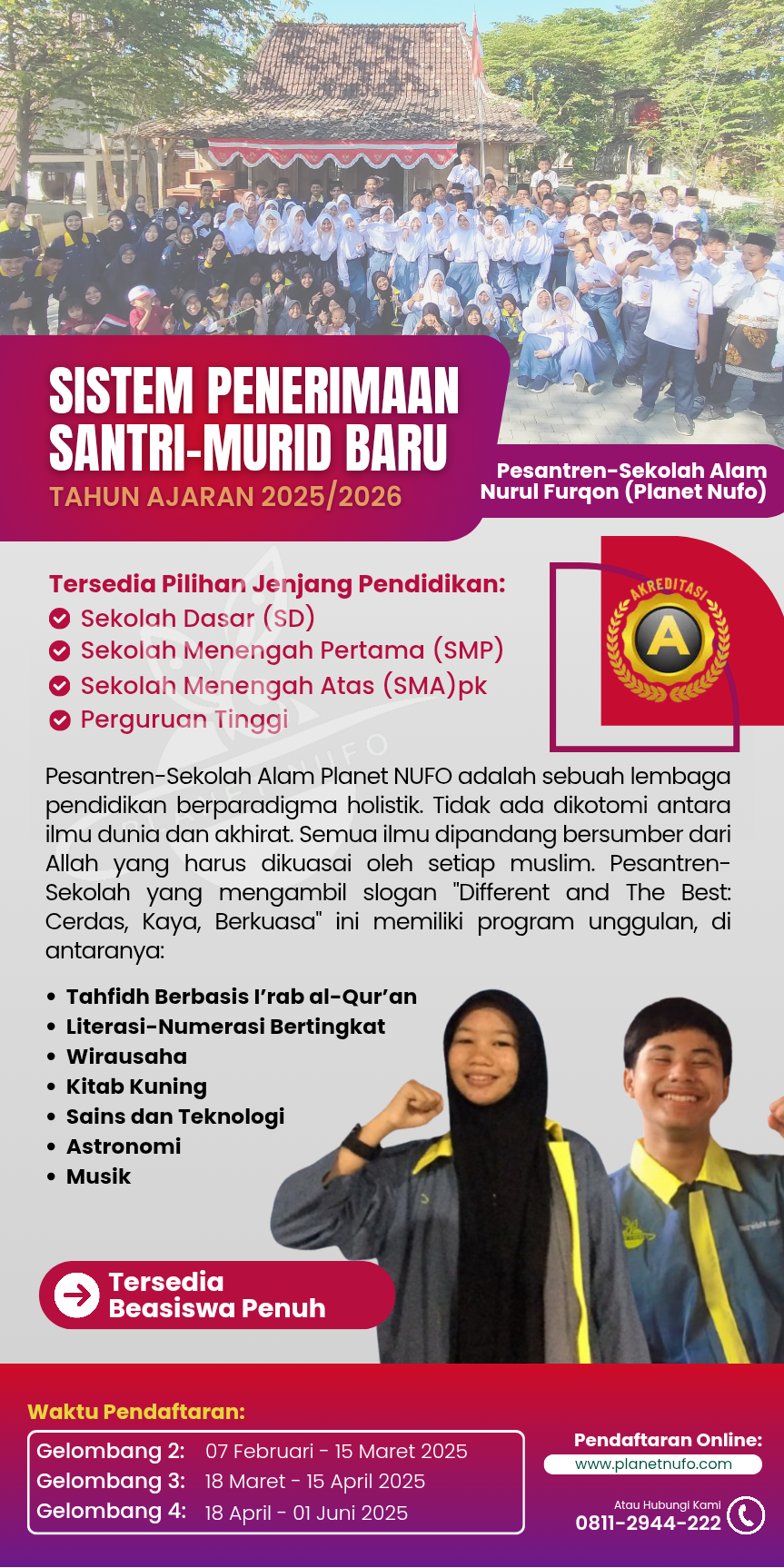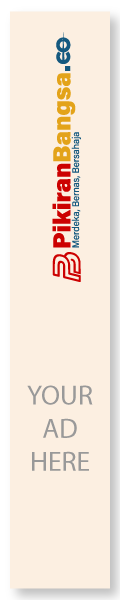Oleh: T.H. Hari Sucahyo, Peminat Masalah Sosial, Budaya, dan Humaniora Penggagas Lingkar Studi Adiluhung dan Kelompok Studi Pusaka AgroPol
Sejarah tidak pernah berdiri di atas netralitas mutlak. Ia selalu lahir dari konteks sosial, politik, dan ideologis yang membentuk siapa yang bercerita dan untuk tujuan apa cerita itu disusun. Ketika negara mengklaim satu versi sejarah sebagai “resmi”, hal itu menandakan upaya monopoli terhadap ingatan kolektif. Inilah yang sedang dipersoalkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dijalankan pemerintah.
Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, menegaskan kekhawatirannya terhadap pelabelan negatif terhadap masyarakat yang bersikap kritis terhadap proyek ini. Ia menanggapi pernyataan Direktur Sejarah dan Kemuseuman, Agus Mulyana, yang menyebut para penolak proyek sejarah itu sebagai “radikal dan sesat sejarah”. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kritik tidak lagi dianggap sebagai bagian dari diskursus ilmiah, melainkan sebagai ancaman yang harus didiamkan.
Kritik juga datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang menyoroti konsep “sejarah resmi” itu sendiri. Menurutnya, penggunaan istilah ini akan menutup pintu bagi interpretasi yang beragam, padahal dalam masyarakat demokratis, sejarah justru harus menjadi arena tafsir yang dinamis. Ia juga memperingatkan bahwa proyek ini bisa mengarah pada kultus individu dan glorifikasi masa lalu secara berlebihan.
Peringatan Usman Hamid tidak berlebihan. Banyak rezim otoriter di dunia telah menggunakan sejarah untuk menutupi kekerasan negara dan membangun legitimasi kekuasaan melalui glorifikasi masa lalu. Dalam bukunya Silencing the Past, Michel-Rolph Trouillot (1995) menunjukkan bagaimana sejarah tidak hanya ditulis, tetapi juga disenyapkan oleh kekuasaan. Apa yang tercatat adalah hasil dari seleksi ideologis atas apa yang pantas dikenang dan apa yang harus dilupakan.
Bahaya dari “sejarah resmi” adalah ia memberikan ilusi objektivitas, padahal sesungguhnya ia merupakan narasi yang sangat dikurasi. Seperti dikatakan oleh Paul Ricoeur dalam Memory, History, Forgetting (2004), sejarah adalah jembatan antara ingatan dan pelupaan. Ketika negara mengambil alih penuh konstruksi sejarah, ia tidak hanya menulis, tetapi juga menentukan apa yang harus dilupakan, biasanya hal-hal yang tidak menguntungkan kekuasaan.
Kita bisa melihat bagaimana peristiwa-peristiwa besar seperti 1965, konflik Timor Leste, atau kasus Tragedi Mei 1998 sering kali didekati secara sepihak dalam narasi resmi. Padahal, narasi korban, saksi, dan komunitas lokal yang mengalami langsung tragedi tersebut memiliki perspektif yang sama pentingnya. Membungkam suara-suara ini demi sebuah “sejarah nasional” adalah kekerasan simbolik terhadap pengalaman nyata manusia.
Sejarah semestinya menjadi ruang dialog dan refleksi, bukan arena pemaksaan versi tunggal. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, semangat kebhinekaan seharusnya juga berlaku dalam cara kita menulis dan memahami sejarah. Seperti yang dikatakan oleh Benedict Anderson dalam Imagined Communities (1991), bangsa dibayangkan bukan hanya melalui batas geografis, tetapi juga melalui narasi bersama yang menghubungkan masyarakat yang tak saling kenal. Jika narasi ini disusun secara eksklusif oleh penguasa, maka yang terjadi bukanlah komunitas imajinatif, melainkan komunitas subordinatif. Upaya pelabelan terhadap kelompok yang kritis terhadap proyek ini sebagai “radikal” atau “sesat sejarah” mencerminkan ketakutan terhadap perbedaan pandangan. Ini adalah praktik delegitimasi yang umum dilakukan dalam rezim otoriter. Bukan kebetulan bahwa narasi sejarah semacam ini sering kali selaras dengan strategi politik pembungkaman wacana.
Dalam demokrasi yang sehat, sejarah bukanlah dogma, melainkan medan tafsir yang terbuka. Akademisi, komunitas korban, budayawan, jurnalis, dan masyarakat sipil punya hak yang sama untuk menulis dan mengkritisi sejarah. Bonnie Triyana menyebut bahwa penulisan sejarah tidak boleh bersifat hegemonik. Dalam praktik terbaiknya, sejarah seharusnya menjadi mosaik dari berbagai fragmen pengalaman manusia, bukan mural tunggal yang dipolitur demi kepentingan penguasa (Triyana, 2024).
Kita juga perlu mempertanyakan: untuk siapa sejarah ini ditulis ulang? Jika untuk rakyat, maka seharusnya suara rakyat juga menjadi bagian integral dalam prosesnya. Sejarah tidak boleh hanya berisi catatan tentang penguasa dan kejayaan negara, tetapi juga harus memuat kisah tentang rakyat biasa, penderitaan korban, perjuangan minoritas, serta suara-suara yang selama ini diredam. Mengutip sejarawan Howard Zinn, “You can’t be neutral on a moving train.” Menjadi netral dalam proyek sejarah resmi yang eksklusif sama saja dengan menjadi bagian dari mekanisme pelanggengan kekuasaan.
Maka, tugas kita sebagai warga negara adalah terus mengawal agar sejarah tidak dikonstruksi menjadi alat propaganda. Kita harus menolak sejarah tunggal dan membuka ruang bagi narasi yang plural. Negara boleh menulis sejarah, tapi bukan berarti satu-satunya yang berhak menuliskannya. Kita berhak bertanya, mengkritik, dan mengingat dengan cara kita sendiri. Sejarah bukan milik negara. Ia adalah milik rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.