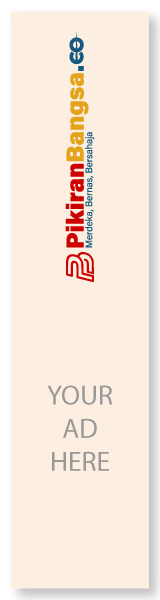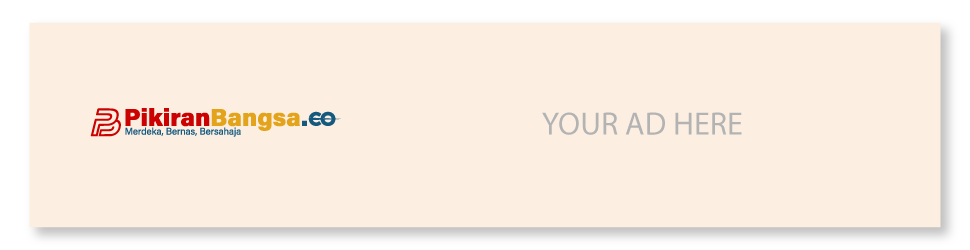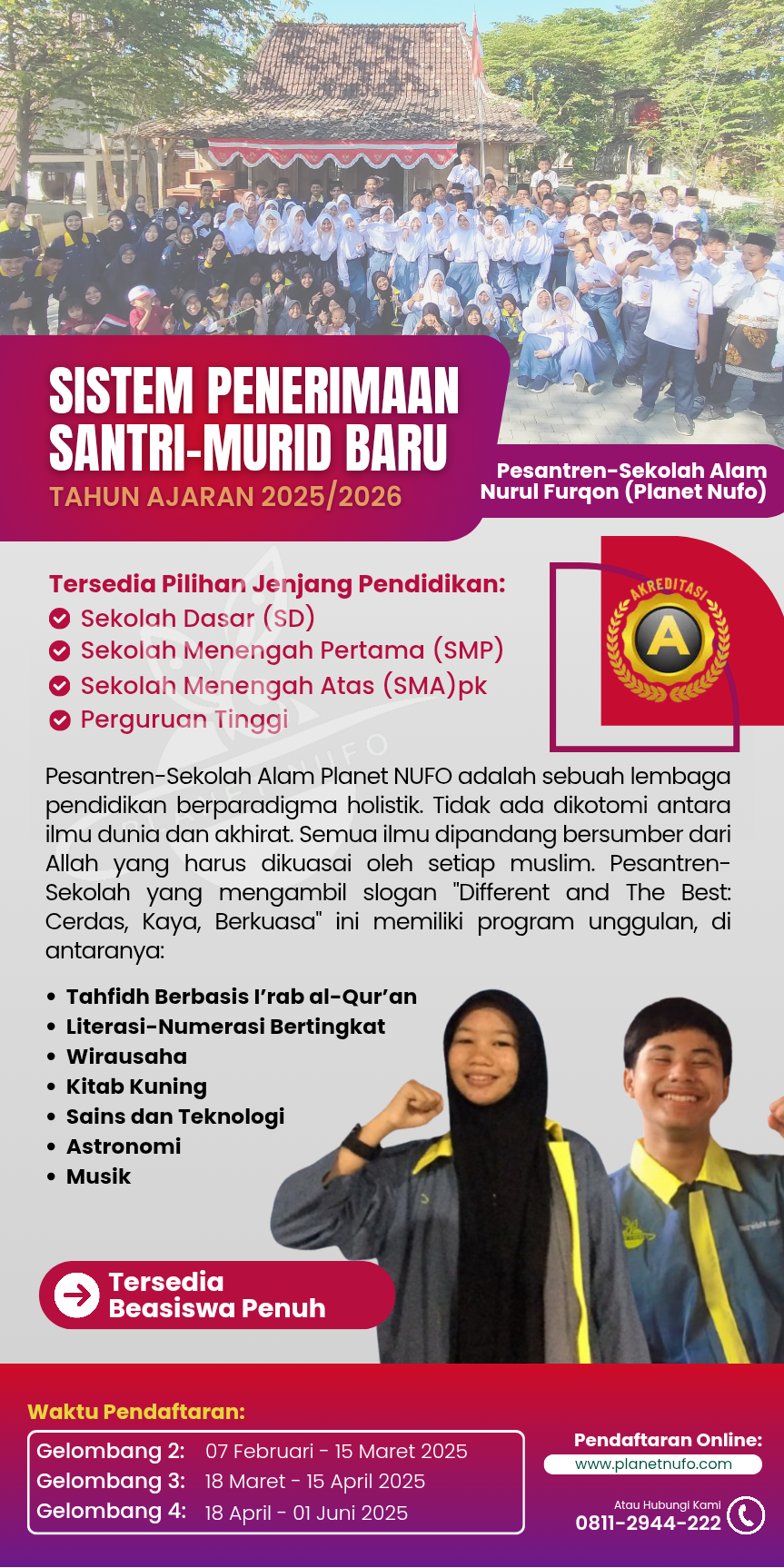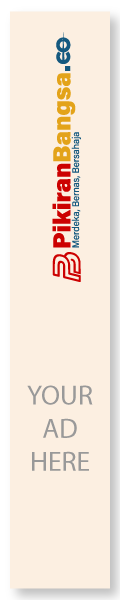Oleh: M. Hikmal Yazid, Aktivis, Pengamat Politik.
Setiap kali Indonesia mendekati pesta demokrasi, panggung politik berubah menjadi pasar malam yang riuh: ramai, penuh janji, dan dibumbui manuver elitis yang menjual harapan sebagai komoditas. Salah satu fenomena paling mencolok yang terus terjadi — bahkan dianggap lazim — adalah terbentuknya koalisi politik tambal sulam, yakni koalisi yang dibangun bukan berdasarkan visi-misi ideologis, melainkan sekadar kepentingan pragmatis lima tahunan. Pertanyaannya: Apakah demokrasi kita sungguh-sungguh lahir dari kesadaran politik rakyat, ataukah hanya proyek besar para elit yang gonta-ganti peran?
Koalisi semacam ini nyaris selalu menafikan arah kebijakan jangka panjang. Partai-partai politik yang sebelumnya saling serang habis-habisan, bisa dalam sekejap bergandengan tangan — bahkan berpelukan — di panggung deklarasi dukungan. Lihat saja Pilpres 2024 lalu, bagaimana partai-partai yang sebelumnya berseberangan secara ideologis dapat bergabung dalam satu barisan, hanya karena kebutuhan menang. Tidak ada penjelasan kepada rakyat tentang bagaimana perbedaan mendasar bisa disatukan, kecuali jawaban normatif: “Demi persatuan bangsa.”
Padahal, dalam sistem demokrasi yang sehat, koalisi dibentuk dari kesamaan ideologi, arah pembangunan, dan prinsip politik yang matang. Bila yang terjadi justru sebaliknya, demokrasi rawan kehilangan substansi. Rakyat hanya diminta hadir lima tahun sekali di bilik suara, lalu ditinggal selama sisa masa jabatan. Demokrasi yang seharusnya berbasis partisipasi aktif, berubah menjadi demokrasi delegatif—rakyat memberikan cek kosong kepada elit yang terus berpindah posisi sesuai peta kekuasaan.
Koalisi tambal sulam juga memperlebar jarak antara rakyat dan pemerintah. Tidak ada lagi garis ideologis yang membedakan partai A dan partai B, sebab semuanya bisa berubah posisi tergantung arus. Ini menyebabkan rakyat bingung memilih, apatis, bahkan tidak lagi percaya terhadap fungsi partai politik sebagai alat perjuangan aspirasi. Partisipasi menurun, kualitas legislasi buruk, dan pengawasan menjadi tumpul karena partai-partai saling menyandera dalam koalisi besar.
Dalam banyak kasus daerah, fenomena ini menjelma dalam bentuk calon kepala daerah yang “diborongkan” oleh hampir seluruh partai. Maka, kompetisi menjadi nihil, kontrol menjadi lumpuh, dan rakyat tak punya pilihan yang setara. Kita seperti menyaksikan demokrasi yang sedang dimonopoli secara sistemik.
Harus diakui, pragmatisme politik adalah cermin dari kegagalan membangun demokrasi berbasis nilai dan kesadaran publik. Ketika partai hanya bertindak sebagai kendaraan kekuasaan, bukan lembaga ideologis, maka rakyat hanyalah penumpang yang tidak tahu mau dibawa ke mana.
Apakah kita akan terus membiarkan siklus ini berulang setiap lima tahun? Jika iya, jangan heran bila demokrasi Indonesia tumbuh tanpa akar. Ia mungkin tampak megah dari luar, tetapi rapuh di dalam. Demokrasi yang hidup dari logika proyek kekuasaan lima tahunan, tidak akan pernah menghasilkan kepemimpinan yang berani berpihak pada rakyat dalam jangka panjang.
Kini saatnya rakyat bersuara lebih keras: mendesak partai-partai untuk kembali ke khittah perjuangan, menolak koalisi instan, dan menuntut transparansi ideologis. Demokrasi bukan soal menang, tetapi soal bertanggung jawab terhadap mandat yang diberikan. Bila tidak, pemilu hanya akan jadi agenda rutin yang merayakan keterasingan rakyat di pangkuan kekuasaan.
Kondisi koalisi politik tambal sulam yang terjadi belakangan ini tidak bisa dibiarkan menjadi normalitas baru. Bila demokrasi hanya dinilai dari seberapa cepat partai bisa membentuk blok kekuasaan tanpa diskursus ideologis, maka kita sedang bergerak menuju masa depan yang penuh kekosongan nilai. Maka, perlu ada rekonstruksi total terhadap makna dan praktik koalisi di Indonesia. Pertama, partai politik perlu membangun sistem kaderisasi dan platform ideologis yang jelas. Pemilih tidak boleh lagi disuguhi wajah-wajah yang hanya populer di media sosial, tetapi minim integritas dan visi. Rakyat berhak tahu: apa yang diperjuangkan oleh partai selain elektabilitas dan kursi kekuasaan?
Kedua, komisi pemilihan umum dan lembaga pengawas demokrasi harus mulai mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat soal transparansi koalisi. Setiap gabungan partai dalam koalisi wajib menyampaikan dokumen tertulis visi bersama, target jangka panjang, serta kontrak politik terbuka kepada rakyat. Bukan cuma deklarasi gemerlap penuh jargon kosong.
Ketiga, masyarakat sipil, kampus, dan media harus terus memainkan peran penting sebagai penjaga nalar politik publik. Jika koalisi dibentuk semata karena negosiasi kekuasaan, publik harus tahu dan punya ruang untuk mengevaluasinya. Jangan sampai media justru ikut menjadi alat normalisasi pragmatisme.
Kita tidak anti pada perubahan sikap politik. Dalam banyak demokrasi, fleksibilitas memang dibutuhkan untuk menyatukan suara dalam pemerintahan. Tapi, politik yang cair harus tetap jernih, bukan keruh karena lumpur kepentingan. Koalisi harus mencerminkan jalan menuju perbaikan, bukan sekadar jalan pintas menuju kursi kekuasaan.
Akhirnya, demokrasi akan selalu menjadi proyek yang belum selesai. Tapi tugas kita bukan hanya ikut memilih, melainkan ikut menjaga: agar politik tidak kehilangan arah, agar koalisi tidak kehilangan makna, dan agar kekuasaan tidak kehilangan malu.