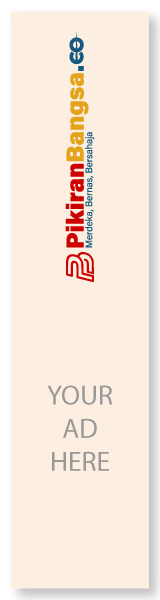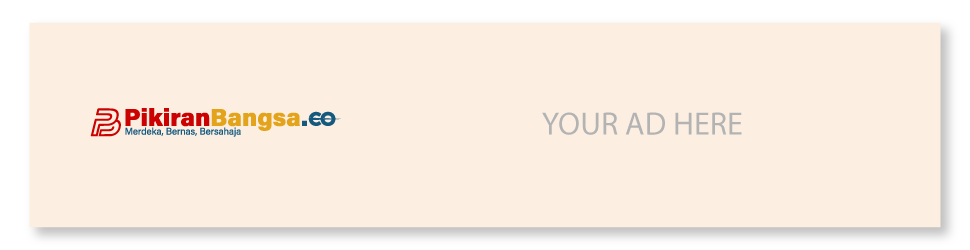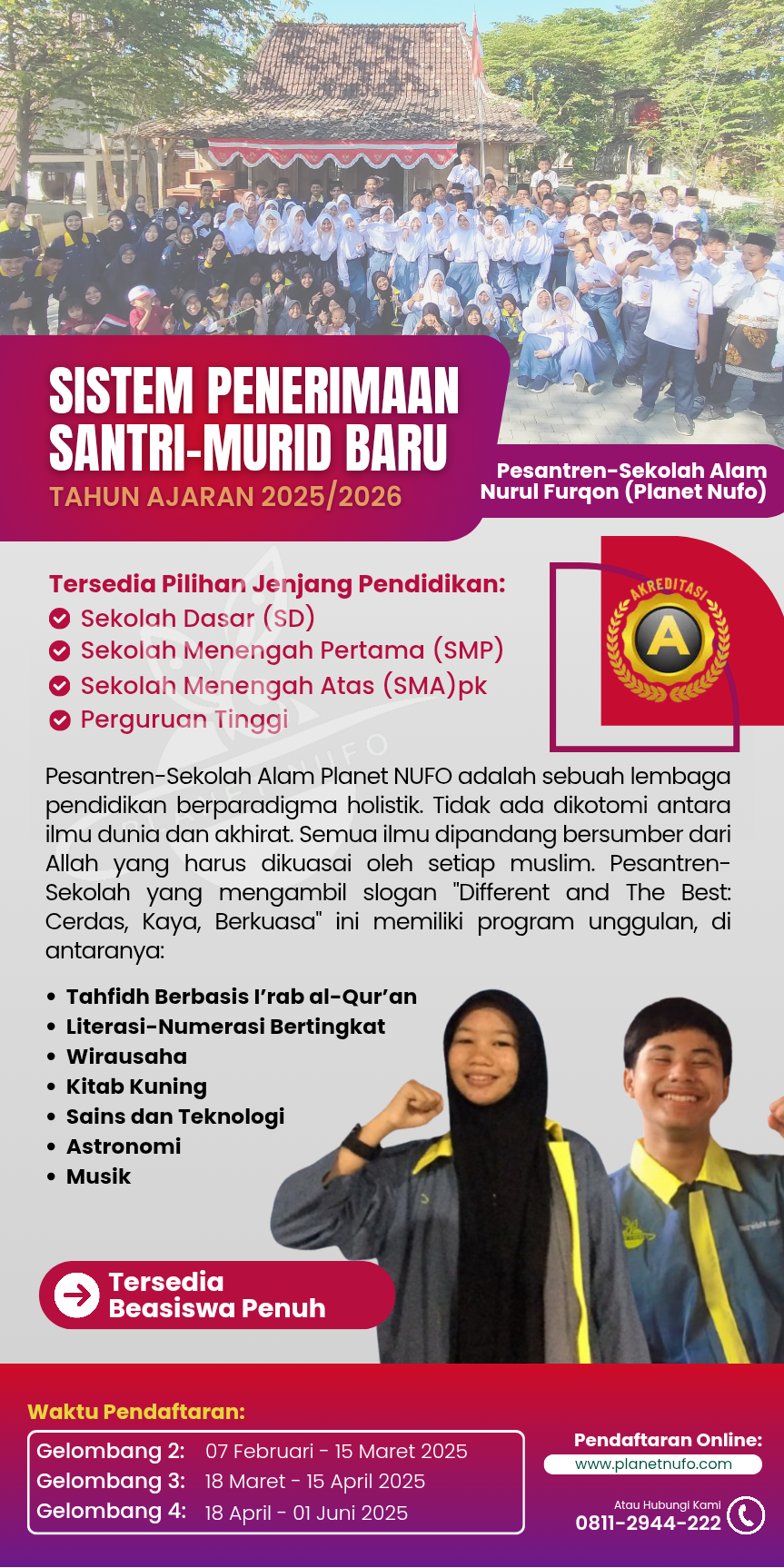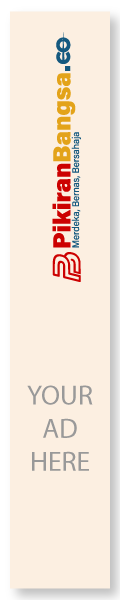Oleh: Ahmad Yusron Chasani, Ketua Badan Pengelola Pesantren (BPP) Pesantren Riset Nggon Ngaji, Kota Salatiga.
Beberapa hari terakhir, linimasa media sosial dipenuhi oleh satu seruan yang menggema: #BoikotTrans7. Tayangan program “Xpose Uncensored” yang menyorot kehidupan pesantren, terutama Pesantren Lirboyo di Kediri, menjadi pemantik gelombang reaksi publik. Potongan video yang menampilkan santri jongkok mengambil susu untuk kiai, disertai narasi “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?”, dianggap merendahkan pesantren dan para kiai.
Di banyak grup WhatsApp, Facebook, hingga ruang diskusi kampus, perbincangan itu menghangat. Masyarakat pesantren merasa disudutkan, seolah lembaga mereka ditampilkan sebagai ruang ketundukan yang menakutkan. Tayangan itu disebut melecehkan, bahkan dianggap memperkuat stereotip bahwa kehidupan pesantren sarat dengan praktik feodal. Di titik inilah, kemarahan kolektif mulai tumbuh.
Namun, jika kita mencoba menarik napas dan memandangnya dengan kepala dingin, polemik ini bukan hanya tentang salah atau benar, tapi tentang bagaimana kita menanggapi dengan bijaksana.
Trans7 memang keliru. Kekeliruan mereka terletak pada cara menyajikan realitas yang kompleks secara sepotong. Dalam dunia jurnalisme, ada tanggung jawab moral untuk menampilkan kebenaran dengan konteks yang utuh. Sayangnya, tayangan itu gagal melakukan hal tersebut. Potongan gambar yang diambil memang nyata, tetapi maknanya berubah ketika dilepaskan dari latar budaya pesantren.
Tradisi santri menghormati kiai bukan bentuk perendahan diri, melainkan ekspresi cinta dan adab. Seorang santri yang mencium tangan gurunya atau menunduk di hadapan kiai melakukannya bukan karena takut, melainkan karena hormat. Saat tindakan penuh makna ini dijadikan bahan narasi yang sinis, tentu saja banyak pihak tersinggung. Di sinilah letak kesalahan Trans7: kurang peka terhadap nilai budaya dan spiritual yang hidup dalam pesantren.
Jika di telisik, tayangan itu seakan tidak memberi ruang bagi pihak pesantren untuk menjelaskan tradisinya. Tak ada konfirmasi, tak ada klarifikasi, dan tidak ada konteks yang seimbang. Padahal dalam prinsip etika jurnalistik, setiap tudingan atau kesan negatif semestinya disertai kesempatan bagi pihak yang disorot untuk berbicara. Karena itu, publik punya alasan kuat untuk kecewa.
Namun, kita juga harus berani melihat bahwa sebenarnya ada hal yang benar dalam langkah Trans7 bukan pada caranya, melainkan pada niat kritis di balik pertanyaan yang diangkat.
Tayangan itu, meski salah dalam penyajian, menyinggung pertanyaan-pertanyaan penting dan fundamen yang jarang dibicarakan secara terbuka, seperti bagaimana transparansi lembaga pesantren dalam mengelola dana umat? Apakah seluruh praktik yang dianggap tradisi masih relevan di zaman modern? Apakah hubungan santri-kiai sudah seimbang antara penghormatan dan kesetaraan moral?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak berarti melecehkan, tetapi mengajak refleksi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia juga perlu terbuka terhadap kritik agar terus berkembang, kritik ini bukanlah bentuk perendahan namun bentuk cinta yang mendalam terhadap pesantren. Dalam dunia yang berubah cepat, tradisi harus berdialog dengan zaman, bukan menutup diri darinya.
Sayangnya, cara Trans7 mengajukan kritik itu justru salah langkah, alih-alih membuka dialog, mereka malah memicu luka (bagi sebagian orang).
Di sisi lain, publik pun perlu belajar menahan diri. Reaksi spontan seperti boikot bisa dimengerti sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan pesantren, tetapi kadang reaksi emosional menutup pintu dialog yang lebih sehat. Media memang patut dikritik, tapi kita juga perlu memberi ruang perbaikan.
Kemarahan sebaiknya diarahkan menjadi kesadaran bersama, yang berarti bahwa media harus berhati-hati dalam menarasikan realitas sosial yang sarat nilai religius, dan pesantren pun perlu lebih aktif menjelaskan maknanya kepada publik. Ketika dua pihak saling memahami, yang lahir bukan hanya klarifikasi, tetapi kepercayaan baru yang penuh keyakinan karena saling memahami.
Kasus boikot Trans7 seharusnya menjadi cermin besar bagi semua pihak. Bagi dunia media, ini adalah pengingat bahwa rating tidak boleh mengorbankan etika. Dalam berita dan dokumenter, terutama yang menyentuh ranah keagamaan, sensitivitas budaya adalah kunci. Pilihan kata, potongan video, dan nada suara bukan hal sepele, semuanya bisa menimbulkan tafsir yang memecah dan bias.
Bagi pesantren, kasus ini adalah momentum besar untuk introspeksi. Apalagi bagi tokoh spiritualnya, dilema akan perilaku akan selalu menghantui jika memang tidak sesuai dengan yang diajarkannya. Pesantren telah lama menjadi benteng moral bangsa, tempat menumbuhkan ilmu, iman, dan adab. Tapi di era digital, pesantren juga dituntut untuk lebih terbuka menjelaskan maknanya kepada masyarakat luas. Bukan hanya untuk membela diri, tapi juga untuk menunjukkan bahwa tradisi bisa berdampingan dengan modernitas.
Akhirnya, kita semua belajar satu hal penting: kebijaksanaan tidak lahir dari amarah, melainkan dari kemauan memahami. Trans7 memang salah langkah dalam pengambilan video dan narasi yang menyinggung. Namun, di balik kesalahan itu, ada benih diskusi yang berharga tentang bagaimana lembaga agama dilihat, dipahami, dan dikritik di ruang publik.
Boikot boleh saja menjadi bentuk protes, tapi penyelesaian sejati lahir dari komunikasi. Tapi jika ini benar terjadi, maka kurang bijak pula hemat saya. Karena banyak sekali mafsadahnya jika boikot massal benar-benar terjadi. Jika media belajar menghormati nilai spiritual, dan pesantren mau berdialog dengan dunia luar tanpa curiga, maka insiden ini tidak akan menjadi luka, melainkan pelajaran.
Dan dari situ, kita belajar bahwa menjadi bijak bukan berarti membenarkan semua pihak, tetapi menempatkan kebenaran di tempat yang adil, dan kehormatan di tempat yang terhormat.