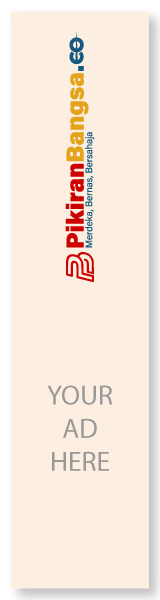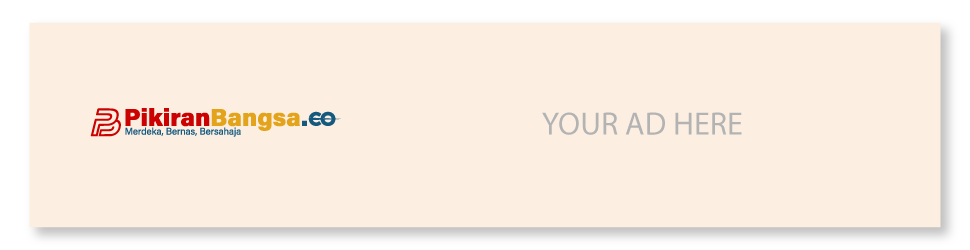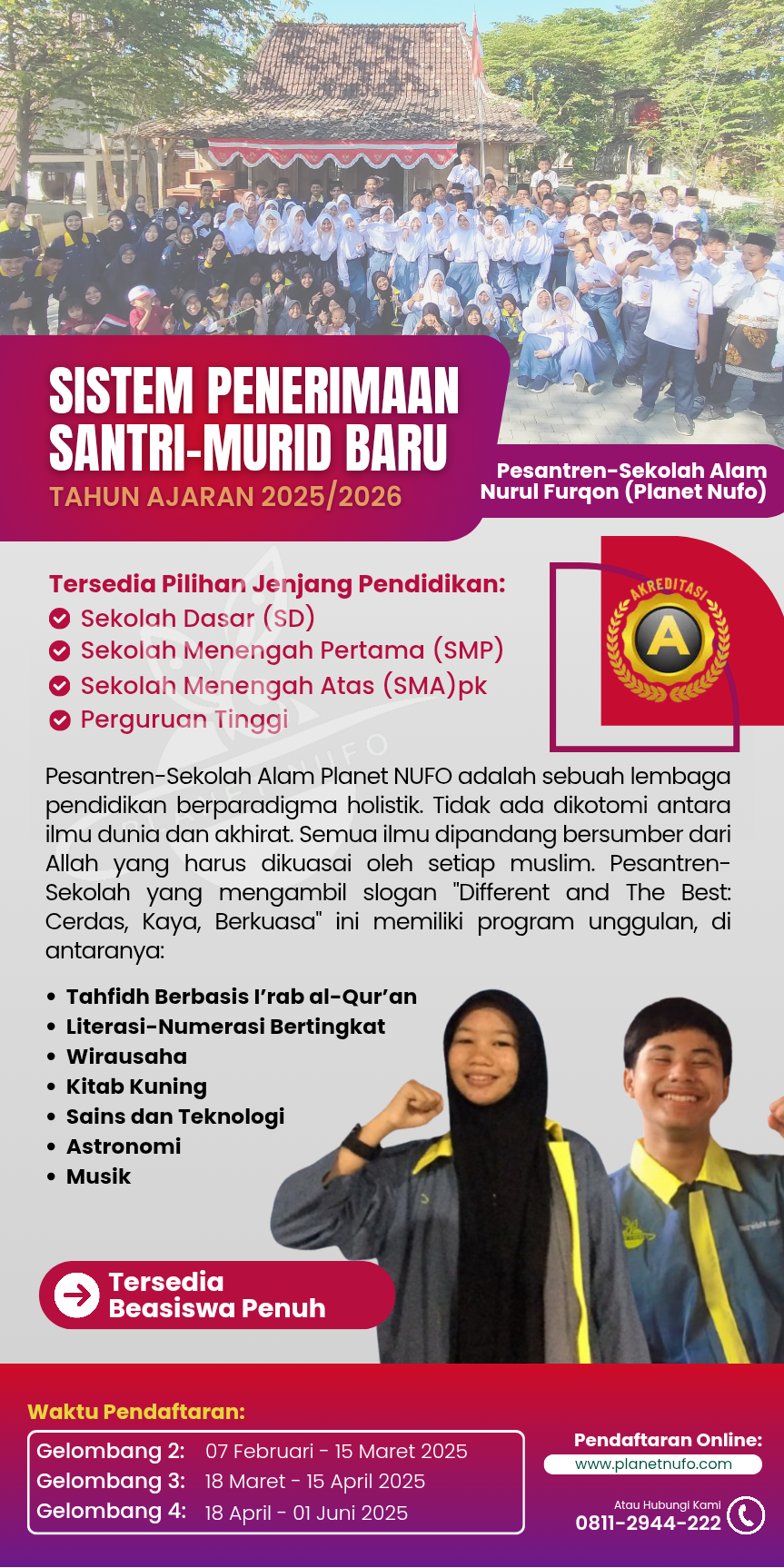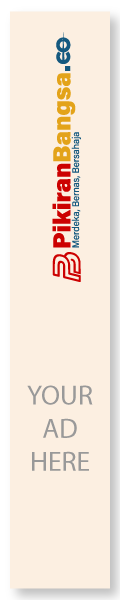Oleh: Muhammad Wildan Maulana, Ketua Umum GPII Kota Semarang 2024-2026
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran besar dalam mencetak generasi Muslim yang berakhlak dan berilmu. Namun, di beberapa pesantren, masih terdapat pola pikir yang bertumpu pada logika mistika. Istilah logika Mistika digunakan oleh Tan Malaka di dalam bukunya yang berjudul “Madilog”. Logika mistika merupakan cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu terjadi disebabkan oleh roh atau hal-hal ghaib, mengedepan nilai-nilai mistik, dan menolak berfikir logis.
Pola pikir ini tidak hanya menghambat kemajuan intelektual santri, tetapi juga berpotensi menjauhkan mereka dari pemahaman Islam yang lebih rasional dan kontekstual.
Logika Mistika di Indonesia berpengaruh besar sejak kemunculannya yaitu pada saat pribumi meyakini kepercayaan animisme dan dinamisme. Keyakinan terhadap hal-hal mistis bertambah ketika negara-negara penjajah menduduki Indonesia.
Mereka memaksimalkan kepercayaan ini untuk dapat semakin berjaya menghegemoni rakyat Indonesia dan mengeksploitasi alam yang ada. Pikiran rakyat dibuat pasif dengan mempercayai hal-hal ghaib dibanding aktif berpikir rasional untuk memecahkan sebuah permasalahan.
Memahami Logika Mistika
Logika mistika yang masih diterapkan di sejumlah pesantren biasanya berupa keyakinan bahwa keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu, mencari nafkah, atau menjalani kehidupan bergantung sepenuhnya pada berkah dari guru, jimat, doa-doa tertentu, atau ritual-ritual khusus. Misalnya, ada santri yang percaya bahwa menghafal kitab tanpa memahami maknanya tetap akan membawa keberkahan jika dilakukan dengan tata cara tertentu. Ada pula anggapan bahwa kesuksesan di dunia bukanlah hasil dari kerja keras dan ilmu, tetapi semata-mata karena “barokah” yang diberikan oleh seorang kyai.
Kepercayaan semacam ini sering kali diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya pesantren. Sayangnya, alih-alih mendorong santri untuk berpikir kritis dan mandiri, logika mistika justru membentuk mentalitas pasif yang kurang menekankan pada kerja keras dan inovasi.
Ada beberapa dampak negatif logika mistika terhadap pendidikan santri. Pertama, menghambat kemampuan berpikir kritis. Pesantren yang masih mengajarkan logika mistika cenderung kurang memberi ruang bagi santri untuk mempertanyakan konsep-konsep yang diajarkan. Kritik atau pertanyaan terhadap ajaran tertentu bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau kurangnya adab kepada guru. Padahal, dalam Islam sendiri, berpikir kritis adalah bagian dari pencarian ilmu yang dianjurkan.
Kedua, memperkuat dogma tanpa landasan ilmiah. Beberapa pesantren masih menanamkan ajaran-ajaran yang lebih bersifat mitos daripada berbasis ilmu. Misalnya, anggapan bahwa seseorang yang tidak mengamalkan ritual tertentu akan mendapatkan kesialan atau tidak akan sukses. Ajaran seperti ini justru menjauhkan santri dari semangat keilmuan yang rasional dan ilmiah.
Ketiga, menciptakan ketergantungan berlebihan terhadap tokoh agama. Dalam lingkungan pesantren yang masih kuat dengan logika mistika, santri sering diajarkan untuk tidak mempertanyakan pendapat kyai atau guru. Segala sesuatu yang dikatakan oleh tokoh agama dianggap sebagai kebenaran mutlak, meskipun terkadang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Hal ini bisa berbahaya karena membentuk pola pikir yang tidak mandiri dan rentan terhadap penyalahgunaan otoritas.
Keempat, kurangnya relevansi dengan tantangan zaman. Di era digital ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Jika pesantren tetap mempertahankan logika mistika, lulusan mereka akan kesulitan bersaing dalam dunia modern yang menuntut pemikiran kritis dan inovasi.
Pesantren Harus Beradaptasi dengan Zaman
Pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan Islam yang maju, tetapi hanya jika mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah:
Pertama, menyeimbangkan antara ilmu agama dan sains. Pesantren perlu mengajarkan Islam secara rasional dengan mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan modern. Misalnya, pembelajaran tentang doa dan keberkahan bisa dijelaskan dengan sudut pandang psikologi dan motivasi, bukan sekadar kepercayaan pada hal-hal gaib tanpa dasar yang jelas.
Kedua, mendorong diskusi dan berpikir kritis. Santri harus didorong untuk bertanya, berpikir kritis, dan menganalisis ajaran yang mereka terima. Sikap kritis bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari proses pencarian ilmu yang sejati.
Ketiga, mengurangi kultus individu terhadap kiai. Penghormatan terhadap guru memang penting, tetapi tidak boleh sampai menciptakan ketergantungan berlebihan. Kyai atau ustaz harus mendorong santri untuk mandiri dalam berpikir dan mengambil keputusan, bukan sekadar mengikuti perintah tanpa memahami alasannya.
Keempat, mengenalkan konsep Islam yang kontekstual dan modern. Pesantren harus membuka diri terhadap berbagai perspektif dalam Islam yang lebih relevan dengan zaman. Misalnya, membahas Islam dalam kaitannya dengan teknologi, ekonomi modern, dan isu-isu global.